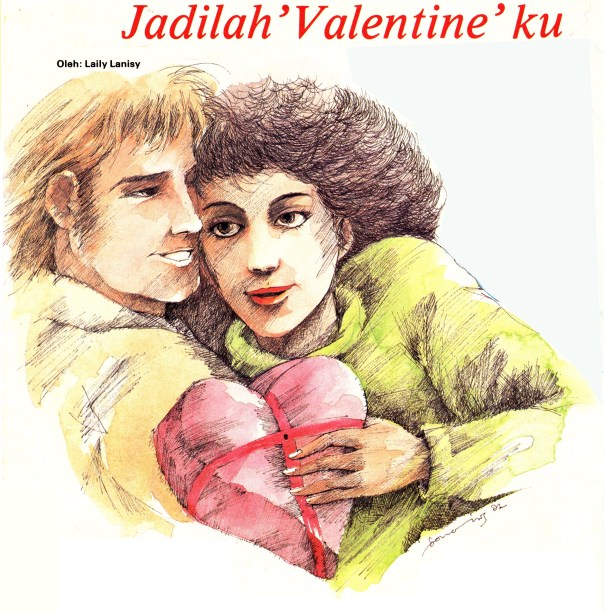Category Archives: Short Stories
“Bu Kar dan Bung Aznen Yang Terhormat …”
Posted by Laily Lanisy
Belum pernah aku merasa begitu khawatir akan umurku seperti sekarang ini. Setiap hari matahari datang dan pergi tanpa meninggalkan pengaruh bagiku. Tahun demi tahun berlalu tanpa sekalipun aku merasa terancam. Setiap tanggal 9 April dengan gembira kurayakan pertambahan umurku. Aku selalu merasa muda. Juga ketika umurku berubah dari 29 menjadi 30 pada tanggal 9 April lalu. Mungkin sampai saat ini aku masih merasa belum perlu khawatir kalau saja Riris, teman kantorku tidak merencanakan perkawinannya.
Ketika Riris mengatakan kalau dia dan Joko akan menikah, aku menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Mereka sudah enam tahun berpacaran. Tetapi beberapa jam kemudian aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bukan pada Riris atau Joko, tetapi pada diriku sendiri.
Aku sadar bahwa semua temanku sudah pada kawin, sudah mempunyai keluarga sendiri. Bahkan sudah sejak bertahun-tahun yang lalu. Nita teman SMU-ku anaknya sudah tiga. Yani, karibku waktu mahasiswa, anak sulungnya sudah masuk SD.
Semakin aku menoleh ke belakang, semakin nyata kalau semua orang yang dekat denganku sudah kawin. Tinggal aku sendiri yang belum. Mending kalau aku sudah merencanakannya seperti Riris. Tapi masalahnya, pacar pun aku tidak punya. Nah, memang benar ‘kan kalau ada sesuatu yang tidak beres pada diriku? Tapi apa?
Aku memang tidak secantik Bunga Citra Lestari. Tapi aku tidak jelek. Orang bilang mataku indah dan hidungku bagus. Tinggiku sedang dan tubuhku proporsional. Dengan IQ 138, aku tergolong cerdas. Aku supel dalam pergaulan sehingga aku bisa diangkat sebagai Manajer Pemasaran pada sebuah perusahaan multinasional. Teman wanitaku banyak. Teman priaku tidak kalah banyak. Hanya sayang tidak seorang pun dari mereka yang merasa cukup dekat denganku untuk melamarku menjadi istri.
Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, pikiran itu begitu menggangguku. Aku yakin ada yang salah dengan diriku. Tapi apa aku tidak tahu. Aku membutuhkan bantuan seorang psikolog. Barangkali.. Ya, barangkali, Ira, psikolog di Departemen personalia bisa membantuku untuk menemukan jawabannya.
Aku tengah memasukkan data ke dalam komputerku, ketika telepon di meja kerjaku berteriak-teriak minta diangkat. Meja kerjaku dengan meja kumputer sengaja aku pisahkan agar tidak setiap saat mataku menatap layar. Kudiamkan saja dengan harapan akan berhenti dengan sendirinya. Ternyata tidak. Krang kring itu masih juga berlanjut hingga semua ujung syarafku berdiri tegang. Terpaksa kutinggalkan komputerku untuk meladeni penelpon yang bawel itu.
‘Selamat siang, Lely di sini.’ Sedongkol-dongkolnya hatiku, ternyata aku masih bisa ramah juga.
‘Buset, Lel, kok lama banget baru diangkat?’ terdengar gerutuan dari seberang. Hanya dua orang di kantor ini yang berani membusetkan aku. General Managerku dan Riris. Dan yang ini jelas suara Riris.
‘Kamu sendiri juga tidak tahu etika,’ sahtku ringan. ‘Kalau lama tidak diangkat letakkan lagi dong. Barangkali saja aku sedang ke toilet.’
Riris tertawa gelak, ‘Aku tahu dengan pasti kalau kamu ada di kamarmu, Lel. Sebelum aku menelpon kusuruh Lusi untuk mengintip ke kamarmu,’ jawab Riris setelah tawanya reda.
‘Ada keperluan apa sih pakai nyuruh orang ngintip segala?’
‘Ini sudah hampir jam dua, Lel. Tidak lapar?’ jawab Riris. Tentu saja dia benar. Kalau kami berdua sedang berada di kantor, kami selalu makan siang bersama di kantin.
‘Sorry, Ris,’ aku mengaku salah. “Sebentar lagi ya? Aku lagi nanggung nih. Sepuluh menit lagi aku ke kamarmu,’ janjiku.
‘Oke, kutunggu kamu sepuluh menit lagi. Jangan lebih. Bisa pingsan aku,’ pesan Riris sebelum menmutuskan hubungan.
Cepat-cepat aku kembali ke komputerku. Beberapa data yang tersisa segera kuinput, untuk mendapatkan analisa kotor. Tepat sepuluh menit kemudian aku sudah berdiri di depan kamar kerja Riris. Dari luar aku bisa mendengar tawa Riris yang nyaring. Bukan tawa orang yang hampir pingsan karena kelaparan.
Masuk ke dalam, aku melihat Riris dan Lusi, sekretarisnya, sedang menghadapi sebuah edisi majalah Femina.
‘Ini kantor atau perpustakaan?’ tanyaku dengan suara yang kubuat seserius mungkin. ‘Perempuan tertawa ngakak. Terdengar si Elang bisa-bisa kalian kena PHK,’ sambungku sambil menyebut nama General Manager kami.
‘Dengar ini, Lel,’ kata Riris tidak menanggapi omonganku. ‘Seorang ibu mengirim surat ke Bu Kar. Dia bilang anak perempuannya yang selama ini merupakan kambing hitam di keluarga, setelah kawin dan punya rumah sendiri jarang mengunjungi ibunya. Padahal si ibu yang menjodohkan mereka dulu. Si anak merasa lebih bebas dan lebih bahagia daripada dulu. Kini si ibu merasa kecewa karena telah menjodohkan anaknya,’ lanjut Riris. Setelah terdiam beberapa detik dia menambahkan. “Lusi, bilang jangan-jangan yang mengirim surat itu ibu Lusi,’ Riris tertawa. Lusi nyengir lucu.
Aku terpana. Sebuah kesadaran menghantam tepat di otak kecilku. Ibu itu mempunyai masalah yang mengganggunya sehingga dia menulis surat kepada Bu Kar. Aku juga sedang mempunyai masalah. Masalah itu juga menggangguku. Mengapa tidak kubawa masalahku ke Bu Kar dan Bung Aznen? Menghadapi Ira yang psikolog dan teman kerjaku sendiri, agak sungkan dan mungkin akan menyiksaku.
Ternyata menulis surat buat Bu Kar lebih sulit daripada menulis cerpen atau membuat laporan tahunan bagi para pemegang saham. Berhari-hari lamanya hanya satu kalimat yang berhasil kutulis. “Bu Kar dan Bung Aznen yang terhormat”. Tidak lebih.
Pernah aku menambahkan seperti ini.
Bu Kar dan Bung Aznen yang terhormat,
Saya seorang gadis Jawa, 30 tahun, manajer pemasaran pada sebuah perusahaan asing, tinggi 161, berat 48, kulit kuning, mata indah, hidung bagus. Berpenampilan menarik. Mendambakan…
Tetapi segera kusobek. Surat seperti ini lebih cocok untuk Kontak jodohnya Kompas daripada rubrik Dari Hati ke Hati.
Pernah pula aku menulisnya dengan lebih hati-hati. Lebih serius dan lebih terinci. Tetapi setelah selesai dan kubaca ulang, aku sadar kalau orang yang kugambarkan di surat itu adalah tokoh fiktif, bukan diriku sendiri. Kuulangi lagi dari awal, tetapi hasilnya masih belum diriku. Begitu terus. Akhirnya Cuma kembali ke Bu Kar dan Bung Aznen yang terhormat.
Sejak aku berniat menulis surat buat Bu Kar dan Bung Aznen, aku selalu meninggalkan kantor sesudah jam tujuh malam. Sesudah jam lima sore, saat jam kerja usai, aku akan segera mengambil flashdisk-ku dan mulai menyusun surat keluhanku.
Sesudah hari kesepuluh dan hampir setengah boks kertas masuk ke keranjang sampah, baru suratku yang berisi curahan hati yang kurasa tidak cengeng berhasil kutulis. Karena waktu itu sudah agak larut, sehabis kucetak segera saja kumatikan komputerku. Tanpa sempat mengambil suratku dari printer, bergegas kukunci kamar kerjaku dan kutinggalkan kantor. Pikirku toh tidak ada seorang pun yang berani mengotak-atik kamarku.
Ternyata aku salah perhitungan. Esok paginya, sesampai di kantor, kulihat kamar kerjaku terbuka. Dan hampir saja aku pingsan ketika melihat suratku buat Bu Kar dan Bung Aznen sudah terletak dengan rapi di atas meja kerjaku dan di sampingnya ada lagi sebuah surat yang lain. Surat balasan!! Dengan kemarahan setinggi Empire Building, kubaca surat tersebut. Begini bunyinya.
Anakku Lely,
Bu Kar dan Bung Aznen sudah mempelajari masalahmu dengan matang. Jawabannya cukup mudah. Hentikan memikirkan dirimu sendiri. Buka matamu lebar-lebar. Ada seseorang yang ingin menjadikanmu sebagai istrinya. Dia begitu dekat. Tetapi karena kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri dengan persyaratan-persyaratan yang tidak masuk akal, maka kamu tidak bisa melihatnya dengan jelas. Buka mata hatimu, kamu akan mengetahui siapa dia.
Salam,
Bu Kar dan Bung Aznen.
‘Mbak Harti!’ teriakku lantang begitu surat tersebut selesai kubaca. Mbak Harti, sekretarisku datang dengan tergesa-gesa. Belum lagi dia berhenti, sudah kuberondong dia dengan pertanyaan.
‘Mbak Harti, siapa tadi yang membuka kamar saya? Siapa saja yang masuk ke sini dan menggunakan komputer saya? Siapa …’ aku berhenti ketika melihat mbak Harti memandangku bingung.
‘Waktu saya datang pintu kamar Mbak sudah sudah terbuka, saya pikir mbak datang lebih dulu. Dan dari tadi saya tidak meihat ada orang yang masuk ke kamar mbak. Kenapa, Mbak? Ada data yang hilang?’ tanya mbak Harti khawatir. Kugelengkan kepalaku sambil mencoba mengingat-ingat apakah aku kemarin lupa mengunci pintu. Tetapi rasanya mustahil. Lalu siapa yang membuka kamarku? Siapa yang telah membaca suratku buat Bu Kar dan Bung Aznen dan menulis surat balasan yang kurang ajar itu?
Hanya aku, mbak Harti dan Karlan, Office Buy kami yang punya kunci pintu kamarku. Dan aku yakin mbak Harti dan Karlan tidak akan berani berbuat sekurangajar itu kepadaku. Jangan-jangan sewaktu membersihkan kamar kerjaku tadi pagi, Karlan lupa menguncinya kembali dan orang lain masuk ke kamarku. Tapi siapa?
‘Mbak Harti, tolong dong panggil Karlan,’ ucapku pelan.
Begitu aku selesai meminta tolong keoada mbak Harti, teleponku berdering. Erlangga, General Manageku. Dia meminta aku segera menemui dia di kantornya. Kalau dia bilang segera, itu berarti benar-benar segera. Dia tidak mau menunggu. Terpaksa urusan pribadiku kutunda.
‘Mbak Harti, saya ke kantor GM dulu. Kalau Karlan datang, suruh dia menunggu sebentar,’ pesanku sambil berlari.
Erlangga Waskita atau si Elang sedang berbicara di telepon ketika aku tiba di depan pintu kamarnya yang terbuka. Dia memberiku tanda untuk masuk dan duduk di depannya. Sementara dia meneruskan pembicaraan teleponnya, aku duduk di depannya dan merasa beruntung mempunyai kesempatan untuk mengamati dirinya dari dekat.
Garis-garis wajahnya adalah garis-garis wajah tipikal orang yang mempunyai kemauan keras, galak, angkuh dan agak dingin. Persis dengan seekor elang. Untung matanya yang kelam selalu bersinar hangat, Dan kalau dia mau tersenyum kerut-kerut di sekeliling bibir dan matanya akan bertambah dalam dan kesan angkuh dan dinginnya sama sekali tidak tampak. Pada umurnya yang hampir empat puluh, Erlangga nampak masih belia. Aku tidak bisa melihat sehelai rambut kelabu pun di rambutnya yang hitam
‘Oke, Lel, bagaimana menurut pendapatmu?’ tanya Erlangga memecah konsentrasiku. Aku tidak tahu sejak kapan dia menghentikan pembicaraan telponnya.
‘Tentang apa?’ tanyaku gelagapan.
‘Tentang aku. Apakah menurutmu aku tergolong ganteng?’ sahutnya ringan. Jadi rupanya di sadar juga kalau aku tengah menilai dirinya. Untuk menutupi rasa maluku aku tertawa.
‘Ya lumayanlah,’ selorohku.
‘Hanya lumayan Hmm..?’ gumam Erlangga dengan senyum di sudut bibirnya. Tapi hanya sedetik. Sedetik kemudian dia sudah kembali angker dan serius.
Dengan singkat dia memberitahu aku bahwa beberapa direksi dari Kantor Pusat dan para manajer pemasaran dari negara-negara Asia Pasifik hari ini tiba di Indonesia dan langsung menuju ke pabrik kami di Surabaya. Erlangga menginginkan agar aku pergi bersamanya ke Surabaya hari ini.
‘Kenapa mendadak?’ tanyaku heran. Baru kali ini orang-orang kantor pusat dan orang-orang penting dari Asia Pasifik datang tanpa gembar-gembor terlebih dahulu.
‘Strategi pemasaran kita untuk bulan depan bocor. Saingan kita, Wheelco, mulai menggunakan strategi yang sama dua hari yang lalu. Kita harus merombak total strategi kita. Ada kemungkinan proposalmu yang tadinya ditolak akan dipakai, asal kamu bisa meyakinkan mereka,’ kata Erlangga. Matanya yang kelam bersinar. Walau sekejap, aku sempat menangkap ada kekaguman dan harapan dalam mata kelam itu.
‘Lalu kapan kita akan berangkat ke Surabaya?’ tanyaku. Adanya kemungkinan bagiku untuk mempertahankan proposal benar-benar membuatku bersemangat.
‘Secepat kamu bisa mempersiapkan bahan presentasi dan perlengkapanmu,’ ucapnya. ‘Kita mungkin harus tinggal di Surabaya untuk dua atau tiga hari,’
‘Oke beri saya waktu dua jam. Saya harus mempersiapkan data terkini dan minta sopir ibu saya untuk mengantar koper dari rumah,’ janjiku.
Kembali ke kamar kerjaku, mbak Harti melaorkan bahwa Karlan hari ini tidak masuk. Laporan yang seharusnya membuatku semakin bingung lagi. Tapi karena ada hal yang lebih penting di kepalaku, aku tidak begitu menanggapinya. Dalam saat-saat seperti ini, aku beranggapan bahwa karierku jauh lebih penting daripada kehidupan asmaraku. Aku tidak peduli kalau aku satu-satunya wanita yang belum kawin. Aku tidak peduli ada orang Aung usil dan mengetahui bahwa sesungguhnya aku kesepian. Sebagai gantinya aku meminta tolong mbak Harti untuk membantuku mempersiapkan bahan presentasi yang harus aku bawa ke Surabaya.
Aku dan Erlangga tiba di Bandara Soetta agak awal. Masih ada waktu sekitar satu jam sebelum penumpang dipersilakan naik ke pesawat. Kesempatan yang ada kugunakan untuk membuka-buka kembali proposal strategi pemasaranku. Aku tidak ingin kedodoran dalam rapat nanti.
Erlangga duduk di sampingku di ruang tunggu eksekutif. Kakinya yang panjang dia selonjorkan ke depan dan bahunya bersandar dengan santai. Matanya mengawasi dengan penuh perhatian ke orang-orang yang ada di ruang tunggu tersebut. Jarang aku melihat dia dalam keadaan santai seperti itu. Biasanya dia selalu serius. Tak peduli dimana pun dia berada, dia tidak bisa duduk dengan diam.
Beberapa menit berlalu. Erlangga berdiri. Menggerak-gerakkan badannya sebentar kemudian melangkah meninggalkanku. Aku tidak tahu berapa lama dia pergi, tahu-tahu dia sudah kembali dengan membawa dua teh botol di tangannya. Yang satu dia ulurkan ke arahku.
‘Terima kasih,’ ucapku sambil memindahkan perhatianku dari dokumen yang ada di pangkuanku.
‘Kamu benar-benar ingin proposalmu yang dipakai ya?’ komentarnya. Aku mengangguk dengan pasti. Dengan Erlangga aku tidak harus malu untuk menunjukkan ambisiku. Ambisi, kata yang kadang dianggap berkonotasi negatif. Tapi bukan oleh Erlangga. Dia tahu dengan pasti aku sudah mencurahkan semua pengetahuan dan keringatku untuk menyusun proposal strategi pemasaran itu.
Sekali lagi Erlangga tersenyum misterius dan kembali duduk di sampingku. Sesudah berdiam diri beberapa saat, Erlangga mendehem. Kututup lagi proposalku dan memandang dia.
‘Lel, boleh aku menanyakan sesuatu?’ ucapnya ragu.
‘Silakan,’
‘Siapa sih Bu Kar dan Bung Aznen itu?’ tanyanya. Dia mengeluarkan pertanyaan itu dengan pelan. Tapi efeknya pada diriku benar-benar hebat. Aku membelalak tidak percaya. Jantungku seakan terbang meninggalkan dadaku.
‘Jadi kamu yang membaca suratku!’ tuduhku dengan kemarahan penuh. Aku tidak tahu bagaimana warna wajahku saat itu. Hanya aku yakin semua darahku naik ke kepala.
‘Tidak dengan sengaja,’ ucap Erlangga seenaknya.
‘Tidak dengan sengaja?’ jeritku.
‘Ayo dong, Lel, jangan teriak-teriak,’ bujuk Erlangga. ‘Surat itu tidak berada di dalam amplop, jadi kukira boleh dibaca oleh semua orang,’ dalihnya.
‘Tapi surat itu ada di dalam kamarku. Dan semua yang ada di dalam kamarku adalah rahasia. Lagi pula untuk apa kamu blusukan ke kamarku?’
‘Dengar baik-baik,’ kata Erlangga dengan nada perintah seorang boss kepada bawahannya. ‘Tadi malam aku menerima telepon dari New York tentang rapat darurat ini. Aku membutuhkan proposalmu. Kutelpon HP-mu tidak aktif. Kutelpon ke rumahmu kamu belum pulang. Aku langsung balik ke kantor. Aku pinjam kunci dari Karlan, masuk ke kamarmu dan mulai menggunakan komputermu. Ketika aku mau mencetak proposalmu, aku melihat suratmu itu masih ada di printer. Maaf, seharusnya aku memang tidak membacanya.’ Kalimat terakhir dia ucapkan dengan tulus.
‘Aku juga teledor,‘ gumamku. Setengah untuk diriku sendiri dan setengahnya untuk Erlangga. ‘Tapi kamu tidak perlu membuat komentar konyol dan menyakitkan seperti itu,’ lanjutku buru-buru.
‘Aku hanya berusaha untuk membantumu,’
‘Oh, ya?’ dengusku tidak percaya.
‘Selama ini aku mengenalmu sebagai orang yang tidak membutuhkan orang lain,’ Erlangga meneruskan tanpa mengindahkan komentarku. ‘Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan kamu tahu bagaimana cara mendapatkannya. Bukan kebiasaanmu untuk meminta bantuan orang lain bila menemui kesulitan. Jadi kalau kamu sampai menulis surat seperti itu, aku menyimpulkan kalau kamu benar-benar membutuhkan bantuan. Nah, aku berniat untuk membantumu.’
‘Dengan merasa iba dan membuat lelucon seperti itu?’
‘Demi Tuhan, Lel, itu bukan lelucon,’ potong Erlangga tajam. ‘Dan tentang iba .. Aku sama sekali tidak kasihan kepadamu. Kalau ada yang harus aku kasihani, itu bukan dirimu. Melainkan pria-pria di sekelilingmu yang selalu merasa yakin kamu tahu apa yang mereka inginkan. Yang merasa tahu kamu menyadari perasaan mereka. Aduh, Lel, sebegitu tololnyakah kamu sehingga kamu tidak tahu kalau cinta itu tidak harus diomongkan, tapi cukup ditunjukkan dengan tingkah laku nyata?’ Sebenarnya Erlangga masih ingin meneruskan pidatonya, untung panggilan untuk menaiki pesawat keburu terdengar. Cepat-cepat kukemasi kertas-kertasku dan kumasukkan ke dalam tas jinjingku.
Selama penerbangan ke Surabaya aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak memulai percakapan dengan Erlangga. Aku takut percakapan itu nanti akan kembali ke masalah surat yang ingin kukirim buat Bu Kar dan Bung Aznen. Dan kalau itu terjadi, aku yakin aku tidak akan bisa mengendalikan emosiku.
Aku berusaha memusatkan pikiranku pada rapat yang akan datang. Mencoba membayangkan situasinya dan kata-kata yang ingin kukemukakan. Tetapi karena Erlangga duduk begitu dekat dan memperhatikan semua gerak-gerikku, hal itu benar-benar sulit. Akhirnya aku menyerah.
‘Kalau kamu begitu pandai membaca orang, mengapa sampai setua ini kamu juga belum kawin?’ serangku tiba-tiba. Kalau aku mengharapkan dia kehilangan keseimbangan, aku salah besar. Erlangga justru tertawa senang mendengar pertanyaanku, Kembali aku merasa dibodohkan.
‘Jadi menurutmu aku sudah begitu tua, ya?’ rajuknya.
‘Bukan itu pertanyaan saya?’
‘Kalau kamu benar-benar ingin tahu jawabannya, Lel,’ ucapnya. ‘aku telah jatuh cinta pada wanita yang tidak tahu bahwa aku sangat mencintainya. Dia sama sekali tidak mempunyai gambaran. Sama sekali,’
Aku tahu dia cuma bermaksud untuk menggodaku dengan pernyataan seperti itu. Tapi aku tidak mau kalah dengan mudah.
‘Kalau dia tidak tahu kalau kamu mencintainya, mengapa tidak kamu beritahu dia?’
‘Terus terang aku takut dia akan menolakku. Persyaratan-persyaratan yang dia ajukan benar-benar tidak masuk akal,’ jawab Erlangga, persis kata-kata yang dia tulis untukku. Kini aku benar-benar bernafsu untuk melecehkannya.
‘Dalam posisimu sebagai general manager, aku tidak percaya kamu tidak berani mengambil resiko,’
‘Aku menunggu saat yang tepat, Lel. Menunggu saat yang tepat,’ gumam Erlangga sambil memejamkan matanya.
Rapat hari itu berjalan dengan alot. Banyak ide baru yang dilontarkan, tapi langsung dibantai dengan sadis. Semua saling beradu kepintaran, beradu pengalaman dan beradu argumentasi. Suara melengking tinggi, dianggap lumrah. Juga gebrakan meja. Dinginnya AC sama sekali tidak mampu untuk mendinginkan kepala.
Ketika giliranku untuk membawakan proposalku tiba, aku tahu aku bakal diserang habis-habisan. Aku sadar aku berada di tengah-tengah dunia yang didominasi pria. Kenyataan bahwa aku wanita semakin membangkitkan ego kelakian mereka. Komentar-komentar sinis, sanggahan-sanggahan keras harus aku hadapi dengan kepala dingin.
Selama aku mempertahankan proposalku dari serangan para manager pemasaran negara lain, Erlangga duduk dengan tenang dan memperhatikan aku dari jauh. Baru kalau aku benar-benar tersudut, dia akan membantuku dengan argumentasi-argumentasinya.
Aku benar-benar lega ketika menjelang rapat ditutup, ide dasar dari proposalku bisa diterima oleh peserta rapat. Besok tinggal membahas dengan tim kecil untuk pekerjaan rincinya.
Keluar dari ruang sidang baru aku merasakan kelelahan yang luar biasa. Dan sewaktu berada di dalam mobil perusahaan yang membawa kami berdua dari pabrik menuju hotel tangan Erlangga merangkul pundakku, aku menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Aku merasa begitu lelah dan membutuhkan perlindungannya.
‘Melihat ketenangamu waktu menangkis serangan para gurita marketing di dalam rapat tadi, aku tidak bisa mempercayai kalau malam sebelumnya kamu menulis surat seperti itu,’ bisik Erlangga di samping telingaku. Suratku untuk bu Kar tentu maksudnya. Tidak ada nada menghina dalam suaranya.
‘Ada saat-saat tertentu dimana aku sama sekali tidak peduli dengan karierku. Saat-saat dimana aku sangat membutuhkan orang yang mengerti aku. Orang yang mengerti kalau aku tidak sekuat yang orang-orang bayangkan,’ sahutku. Aku tidak peduli apakah sopir kami menguping percakapan kami atau tidak.
‘Saat seperti ini?’ ajuk Erlangga sambil mempererat pelukannya. Entah mengapa aku menganggukkan kepalaku. Barangkali karena kau sudah terlalu capai untuk berdebat.
‘Kalau begitu tidak ada saat yang lebih tepat dari sekarang ini,’ ucap Erlangga. Aku tidak tahu arah dari ucapannya itu. Aku melepaskan diri dari tangannya dan memandang dia dengan heran.
‘Kamu ingat pertanyaanmu yang terakhir di pesawat siang tadi?’ tanyanya. ‘Kamu bertanya mengapa aku tidak mau mengambil resiko dan melamar gadis yang kucintai. Dan kujawab, ‘Aku menunggu saat yang tepat, Lel’ Ingat?’ tanya Erlangga. Setelah mengambil nafas dalam dia melanjutkan. “Kurasa sekarang adalah saat yang sangat tepat. Kamu terlalu capai untuk menolak lamaranku. Ya ‘kan?’
‘Erlangga Waskita, mengapa berbelit-belit? Aapakah kamu sedang mencoba mengatakan sesuatu kepadaku?’ tanyaku tidak sabar.
‘Tentu saja, tolol,’ tukasnya. ‘Aku sedang melamarmu. Aku tidak berani melakukannya selama kamu penuh energi dan merasa tidak membutuhkan orang lain.’
Aku tergelak mendengarkan ocehannya. ‘Elang, aku benar-benar menghargai niatmu untuk membantuku,’ kataku. “Tapi kamu tidak harus mengorbankan dirimu sendiri dengan melamarku seperti itu,’
‘Lely, ternyata kamu lebih buta dari yang kuperkirakan. Ketika aku menulis surat balasan kemarin malam, aku memang mencoba untuk membantumu untuk membuka mata hatimu. Tapi kalau aku melamarmu sekarang, ini untuk kepentinganku sendiri. Sudah terlalu lama aku menunggumu untuk menyadari bahwa aku mempunyai perhatian khusus kepadamu. Menyadari kalau diam-diam aku ingin lebih dari sekedar atasanmu. Terlalu lama aku makan hati mendengar jawabanmu setiap kali ada orang yang menanyakan kapan kamu berniat untuk kawin. Oh, sampai sekarang saya belum butuh suami. Saya lebih suka hidup sendiri. Kamu pikir enak mendengar perkataan seperti itu setiap saat?’
‘Ayo dong, Lang, berhentilah bercanda. Aku lagi capai,’
‘Siapa yang bercanda? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kalau orang menyatakan cintanya melalui isyarat, kamu tidak bisa menangkap artinya. Kalau diucapkan, kamu tidak menganggapnya serius. Bagaimana caranya agar aku bisa meyakinkanmu?’
‘Jadi kamu serius?’
‘Tentu saja aku serius. Sesampai di hotel nanti, aku ingin kamu menelpon orangtuamu dan membertahukan kepada mereka kalau sekembali kita dari Surabaya aku akan meminangmu dan kita akan segera kawin.’
‘Erlangga kamu benar-benar gila. Kamu mengajak kawin dan sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk berpikir dan mencernanya terlebih dahulu.’
‘Betul. Aku ingin mendengar jawabanmu sekarang. Aku tidak mau menunggu. Apalagi menunggu setelah proposal pemasaranmu diterima dan dilaksanakan. Kamu akan merasa terlalu sukses dan tidak membutuhkan teman hidup lagi,’
‘Kamu salah, Lang. Kesuksesan itu tidak akan berarti bagiku kalau tidak ada orang lain yang ikut menikmatinya.
‘Apakah itu berarti kamu menerima lamaranku?’
“Aku tidak tahu. Berilah aku kesempatan. Paling tidak sampai kita tiba di hotel,’
Malam itu, sesudah menelpon ayah dan bunda di Jakarta dan sebelum tertidur, aku sempat memikirkan tentang Bu Kar dan Bung Aznen. Belum sempat suratku kukirim, aku sudah menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaanku. Terima kasih, Bu Kar. Terima kasih, Bung Aznen.
Posted in Short Stories
Tags: Cerpen, Femina, Fiction, Indonesian Fiction, Indonesian Short Story
Gotehan
Posted by Laily Lanisy
Nita, sepupuku, menentangku ketika kukatakan aku akan menyetir mobil sendiri ke Gotehan. Dia mengingatkan kalau aku belum terbiasa untuk menyetir di ruas jalan sebelah kiri dan menawarkan sopirnya untuk mengantarku. Dengan tegas kutolak tawarannya. Nita tidak kenal putus asa dan terus beragumentasi dengan panjang lebar. Dia baru berhenti sesudah kukatakan kalau aku ingin menghadapi masalahku seorang diri.
Namun begitu keluar dari kota Surabaya aku mulai menyesali keputusanku. Truk-truk, bis-bis serta kendaran-kendaraan lain yang berseliweran tak beraturan benar-benar membuatku ngeri. Menghadapi kemacetan di depan pasar Krian nyaris membuatku berputar dan mengurungkan niatku. Untung aku segera sadar kalau jalan yang aku tempuh sudah terlampau panjang. Aku sadar kalau kehidupanku tidak akan kembali normal sebelum aku pergi ke Gotehan.
Minggu lalu kehidupanku masih berjalan dengan normal. Senin pagi aku masih menuju ke kantorku yang berada di Embarcadero, San Francisco dengan berbagai proposal investasi yang aku siapkan selama akhir pekan. Namun kenormalran itu seakan berhenti di depan meja Pam, resepsionis kami. Setelah mendesahkan sapaan selamat paginya yang khas, Pam menjelaskan kalau ada seseorang yang sedang menungguku di meeting room.
‘Pam, ini baru jam setengah enam.’ protesku. ‘Kamu tahu aku tidak pernah menerima tamu sebelum jam sembilan.’
Karena waktu New York yang tiga jam lebih awal dibanding San Francisco, para fund manager perusahaan-perusahaan investasi di San Fransisco, sudah harus siaga di kantor sebelum jam enam pagi untuk menunggu saat dibukanya bursa efek di New York. Sudah berkali-kali kuingatkan Pam, walaupun aku sudah berada di kantor aku belum mau menemui tamu sebelum jam sembilan pagi. Tiga jam pertama biasa kumanfaatkan untuk bekerja di depan monitor.
‘Bukan tamu biasa, Lei,’ kilah Pam, ‘Dia saudaramu dan dia sudah menunggu lebih dari setengah jam.’
‘Saudara? Ayolah, Pam, aku tidak punya saudara disini.’
‘Aku yakin dia saudaramu. Wajah kalian mirip sekali.’ Jawab Pam pasti. Aku tidak mau berdebat lagi. Bagi Pam semua orang berkulit coklat mempunyai wajah yang sama. Bila bertemu orang Hawaii dia akan bilang kalau mereka mirip aku. Bertemu orang Thailand dia bilang saudaraku. Bertemu orang Philipina apalagi. Jadi waktu memasuki ruang rapat aku sudah siap untuk bertemu dengan orang yang berasal dari negara manapun. Bahkan orang Brazil atau Argentina sekalipun.
Ternyata observasi Pam kali ini tepat. Bukannya tamuku mirip aku, tapi dia memang orang Indonesia. Berusia sekitar empat puluhan dengan postur dan tinggi yang sedang. Ketika melihat aku masuk ruangan dia segera meletakkan dokumen yang sedang dibacanya, berdiri dan mengulurkan tangannya ke arahku.
‘Leily ?’ tanyanya. ‘Saya Satrio dari Kantor Pengacara Satrio, Bonar dan……’ siapa aku tidak ingat. Mungkin gara-gara terkejut mendengar kelanjutan kata-katanya.
‘Saya diminta keluarga Sukarsono untuk menemui Anda…’ lanjut Satrio pelan. Namun yang pelan itu mampu untuk menggoncangkan diriku dengan dahsyat. Lututku bergetar dengan hebat. Cepat-cepat aku duduk di kursi yang terdekat.
‘Leily, Anda masih ingat kan dengan keluarga Sukarsono ?’ tanya Satrio menyalahartikan kebisuanku. Tentu saja aku masih ingat. Bagaimana aku bisa melupakan mereka bila aku pernah sangat mencintai salah satu di antara mereka.
‘Leily..?’ tanya Satrio. Kuanggukkan kepalaku sambil menunggu kata-kata selanjutnya.
‘Apakah Anda tahu kalau Bapak dan Ibu Nugra Sukarsono sudah meninggal dunia?’ tanya Satrio tanpa ekspresi. Aku tersentak.
‘Kenapa ? Kapan ?’ tanyaku kaget.
‘Ibu Sukarsono meninggal tiga tahun lalu karena sakit jantung dan Bapak meninggal selang beberapa bulan kemudian karena gagal ginjal.’ Aku terpaku. Apapun yang pernah mereka lakukan terhadapku, kabar tersebut tetap menyedihkanku juga. Kasihan Pra.. Dia pasti sangat kehilangan mereka.
‘Sejak beliau berdua meninggal dunia, kami berusaha mencari Anda. Semua keluarga Anda yang kami hubungi tidak ada yang bersedia memberitahu dimana Anda berada. Keluarga Anda sangat setia. Beberapa bulan kami sempat menghentikan pencarian kami, karena jejak yang kami telusuri berkali-kali buntu .’
‘Mengapa kalian mencari saya ? Apakah kalian akan menuduh saya sebagai penyebab kematian mereka ?’ tanyaku defensif. Satrio menggelengkan kepalanya.
‘Nama Anda tercantum sebagai salah seorang yang mendapatkan pekebunan cengkih di Gotehan, Jombang serta…’
‘Apa ?’ sergahku.
‘Lima tahun yang lalu Bapak dan Ibu Sukarsono membuat wasiat yang mencantumkan Anda dan Pradipta sebagai ahli waris terhadap perkebunan cengkih mereka. Ada juga beberapa kekayaan lain diserahkan khusus untuk Anda. Saya membawa daftarnya disini.’ Satrio menjelaskan sambil menunjuk tas kerjanya.
‘Anak-anak keluarga Sukarsono juga heran mengapa Anda masuk sebagai ahli waris. Tidak dijelaskan alasan mengapa mereka memasukkan nama Anda. Sekarang, dengan harga cengkih yang jatuh Pradipta berniat untuk menjual kebun tersebut. Ada seorang pengusaha yang berniat membeli tanah tersebut untuk dijadikan hotel. Namun, tanpa persetujuan Anda, Pradipta tidak bisa menjualnya.’
‘Saya tidak mau kekayaan mereka. Mereka boleh melakukan apa saja terhadap kekayaan mereka. Saya tidak peduli. Saya akan menulis pernyataan bahwa saya menolak manjadi ahli waris mereka dan Anda bisa menjadi saksinya.’ ucapku cepat.
‘Untuk kekayaan yang lain mungkin bisa kita lakukan,’ ucap Satrio sabar, ‘tapi khusus tanah yang di Gotehan ada klausal khusus yang menyatakan bahwa Anda dan Pra– boleh bersama maupun sendiri– harus menandatangani persetujuan penjualan di depan lurah Gotehan. Kalau saja lurah Gotehan tidak terlalu tua untuk saya ajak kesini, akan saya ajak kesini sehingga kami tidak harus menyusahkan Anda. Pradipta berpesan kepada saya agar kami tidak menyusahkan Anda.’
‘Bagaima kabarnya ?’ aku tidak kuasa untuk tidak menanyakannya.
‘Pradipta ? Oh, dia baik-baik saja. Dia sangat sukses dalam memimpin perusahaan keluarganya,’ cerita Satrio. ‘Sebelum berangkat kesini saya sempat makan siang di kantornya dengan dia dan anak…’
‘Anak ?’ potongku tanpa sadar.
‘Oh, Anda belum tahu? Pra mempunyai anak perempuan berusia empat atau lima tahunan yang sangat dibanggakannya. Cantik mirip sekali dengan Pra…’ lanjut Satrio tanpa menyadari kebekuanku. Tiba-tiba wajah Anggita berkelebatan di kepalaku. Anggi yang tidak pernah dikenal ayahnya apalagi dibanggakannya. Hatiku seakan terhimpit batu. Tiba-tiba muncul tekadku untuk melepaskan diriku dan Anggita dari semua ikatan masa laluku. Aku ingin bebas sebebas-bebasnya dari pengaruh keluarga Sukarsono. Bila untuk itu aku harus datang ke Gotehan aku akan datang.
Setelah beberapa kali jip yang kupinjam dari Nita nyaris tergilas truk gandeng akhirnya sampai juga aku di depan menara air menjelang kota Jombang. Kubelokkan mobil ke kiri meninggalkan kebisingan jalan raya dengan kendaran-kendaraan kelas beratnya. Beberapa saat kemudian aku mulai memasuki jalan desa yang mulus yang diteduhi rindangnya pohon-pohon yang berjajar di kiri dan kanannya. Hanya sesekali mobilku berpapasan dengan sepeda motor dan gerobag sapi
Tanpa kusadari anganku membawaku kembali ke masa lampau. Ke masa ketika aku masih begitu naif. Masa ketika duniaku berputar di sekeliling Pra. Masa dimana Pra mengajakku melewati jalan-jalan desa ini sambil mengunyah kacang rebus yang kami beli di mulut pinto tol Mojokerto. Sambil sesekali kami ikrarkan cinta dan kesetiaan.
Setamat sekolah aku bekerja di bagian Marketing Perusahaan Keluarga Sukarsono, salah satu perusahaan terbesar di Surabaya. Pada waktu itu Perusahan memegang lisensi beberapa sepatu olahraga dari Korea dan sedang mencoba menjajagi kemungkinan untuk sepatu kulitnya. Karena aku seorang akuntan dan lumayan dalam menulis proposal aku dilibatkan di dalam team Pradipta yang bertanggung jawab terhadap Pengembangan Perusahaan. Kami sering mengerjakan proyek bersama.
Lama kelamaan, hubungan yang tadinya bersifat profesional berubah menjadi pribadi. Sangat pribadi. Agar tidak menjadi gunjingan di kantor, Pradipta meminta agar hubungan kami dirahasiakan. Aku menurutinya. Pradipta menjelaskan kalau dia tidak bisa mengajakku jalan-jalan di Surabaya karena takut ketahuan orang. Aku memahaminya. Sebagai gantinya setiap akhir pekan Pradipta mengajaku menyusuri jalan-jalan desa ini menuju perkebunan cengkihnya.
Alangkah bodohnya aku. Tentu saja Pradipta tidak menginginkan hubungan kami diketahui orang. Dia sudah bertunangan dan akan kawin dalam waktu dekat. Sayangnya aku terlambat mengetahui hal tesebut. Sangat terlambat.
Seumur hidupku aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Saat itu Pradipta sedang berada di Jepang. Dari Jepang dia mengabarkan kalau Perusahaan kami telah memenangkan tender. Ayah Pradipta merayakan keberhasilan tersebut dengan mengundang kami semua makan malam bersama keluarganya di rumah mereka.
Pada saat kami tengah menikmati hidangan, Pak Nugra memperkenalkan anggota keluarganya. Sebagai wakil dari Pradipta yang belum pulang, dia memperkenalkan calon istri Pradipta. Ratih. Wanita yang sangat cantik, anggun dan nampak sangat dewasa. Wanita yang pas sekali dengan Pra.
‘Tiga bulan lagi Pradipta dan Ratih akan melangsungkan perkawinan mereka. Kami harap kalian semua bisa menghadirinya.’ Pak Nugra mengakhiri sambutannya dan sekaligus mengakhiri hidupku.
Kepedihanku tidak berhenti disitu. Usai makan malam, pak Nugra meminta aku untuk tinggal. Kemudian di depan istri, anak-anak dan calon menantunya dia mengatakan kalau Pradipta telah meminta dia untuk menyampaikan kepadaku agar aku tidak salah menafsirkan perhatian Pradipta. Pradipta tidak pernah mencintaiku dan berharap agar aku tidak mengejar-ngejar dia lagi.
‘Kami mengerti perasaanmu, Leily.’ ucap ibu Pradipta manis tapi berbisa. ‘Untuk menghindari rasa malumu di depan teman-teman kantor, mulai besok kamu tidak perlu ke kantor lagi. Pak Nugra telah menyuruh bagian penggajian untuk mentransfer gaji terakhirmu serta sekedar uang jasa yang dapat kamu pergunakan untuk biaya hidup sebelum kamu mendapatkan pekerjaan lain……’ Aku tidak mendengar kelanjutan kata-katanya. Aku berlari dan berlari tanpa pernah menoleh lagi.
Enam bulan kemudian kulahirkan Anggita.
Jalan di depanku mulai menanjak dan berkelok. Kumatikan AC mobil dan kubuka jendela lebar-lebar. Kubiarkan angin pegunungan yang lembut membelai rambutku. Sebutir air mata bergulir di pipiku. Oh, betapa aku mencintai tempat ini.
Karena tidak mengetahui dimana rumah lurah Gotehan, mobil kuarahkan langsung ke rumah kebun keluarga Sukarsono. Aku akan meminta ibu Warti, perawat rumah itu untuk mengantarku ke rumah pak lurah.
Rumah kayu di atas bukit berlatar belakang rimbunnya hutan cengkih itu masih persis seperti yang kuingat. Rasa-rasanya baru minggu lalu aku dan Pra menghabiskan waktu kami disitu.
Kuparkir mobilku di tempat pengeringan cengkih. Begitu aku meloncat dari mobil, entah dari mana munculnya, ibu Warti telah berdiri di depanku.
‘Non Leily, saya tidak percaya kalau Non benar-benar datang.’ isaknya dengan mata berkaca-kaca. ‘Mas Pra meminta saya membersihkan dan menyiapkan kamar untuk Non. Katanya sewaktu-waktu Non akan datang.’
‘Mas Pra sering kesini ?’
‘Enggak, Non. Sejak Non pergi mas Pra enggak pernah kesini lagi.’ jawab bu Warti. ‘Tiba-tiba minggu lalu mas Pra muncul dan bilang kalau Non akan datang.’
Sesudah ditelpon Satrio, pikirku.
Setelah selesai meributkan aku yang tidak membawa koper dan tidak berniat untuk tinggal lama di Gotehan, bu Warti menuntunku memasuki rumah Kalau dari luar rumah itu nampak tidak berubah, ternyata di dalamnya banyak perubahan. Di salah satu sisi ruang tamu yang tadinya hanya jendela-jendela kecil sekarang telah berubah menjadi kaca besar sehingga dengan bebas dapat memandang keluar. Pohon-pohon cengkih yang tadinya menghadang di depannya sudah ditebang diganti dengan hamparan padang rumput. Dari tempatku berdiri aku bisa memandang ke bukit seberang. Di atas bukit seberang ada sebuah rumah peristirahatan dengan kolam renang infinity di bibir tebing.
‘Non, ini ada titipan surat dari ibu,’ ibu Warti muncul kembali memecahkan keheningan. ‘Ibu berpesan kalau saya harus menyimpan surat ini baik-baik dan hanya memberikannya kepada Non’ lanjutnya sambil mengangurkan sebuah amplop.
‘Kapan diberikannya ?’
‘Sebulan sebelum beliau wafat.’ jawab bu Warti. Aku duduk dan pelan-pelan kubuka surat tersebut. Surat dengan tulisan tangan yang indah.
Leily, anakku (kalau engkau mengijinkan aku untuk memanggilmu demikian)..
Sebenarnya aku berharap dapat mengatakan ini semua langsung kepadamu. Tapi dengan kondisi kesehatanku yang semakin memburuk, aku tidak yakin kalau Tuhan memberiku kesempatan untuk bertemu lagi denganmu. Namun aku percaya suatu saat nanti kamu akan datang ke Gotehan dan membaca suratku ini.
Pertemuan kita yang terakhir telah berubah menjadi tragedi. Bukan hanya untukmu, Leil, tapi juga untuk keluarga kami. Kami telah lancang mencampuri urusan pribadi kalian. Kami merasa kamilah yang paling tahu apa yang akan membuat Pradipta berbahagia. Kami sadar tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan tindakan kami terhadap kalian berdua.
Sewaktu Pra pulang dan mengetahui apa yang terjadi, hidupnya berakhir disitu. Baginya matahari tidak pernah bersinar lagi. Seketika Pra menjadi orang asing bagi kami. Tanpa emosi sama sekali. Kalau dia marah kepada kami dia tidak tunjukkan kemarahannya. Tapi sejak saat itu kami tidak pernah lagi mendengar tawa dan candanya. Kami tidak bisa meraih hatinya.
Pernah kusarankan kepadanya untuk mencarimu. Dia tidak mau. Dia bilang kalau kau benar-benar mencintainya dan mempercayainya, kamu tidak akan meninggalkannya.
Kami tidak menyalahkanmu, Leil. Kamu masih begitu muda dan kami terlalu kejam terhadapmu.
Karena Pra tidak mau mencarimu, maka aku dan ayah Pra melakukannya untuknya. Ternyata mencarimu sangat sulit.. Keluargamu tidak ada yang bersedia berbicara kepada kami. Permintaan maaf kami yang bertubi-tubi tidak menggemingkan mereka. Itu merupakan awal dari kecurigaan kami kalau hubuganmu dengan Pra lebih dalam dari dugaan kami.
Dari bu Warti kami mendengar kalau kamu dan Pra sering menghabiskan waktu kalian di Gotehan. Gotehan merupakan rumah cinta kalian berdua. Firasatku mengatakan kalau pada waktu kamu meninggalkan Surabaya, kamu tengah mengandung anak Pra, cucu kami.
Aku hampir gila memikirkan itu. Setelah aku mengemis ribuan kali dan penyakit mulai menggerogotiku, akhirnya ibumu mau mengatakan kalau kamu telah melahirkan anak perempuan. Tanpa informasi mengenai nama anakmu, dan dimana kamu dan cucuku berada. Ibumu juga meminta kami untuk tidak mengatakan hal itu kepada Pradipta. Beliau meminta kami untuk tidak mengganggu ketenanganmu.
Aku hormati permintaan itu, walau dengan hati yang sangat berat. Ingin rasanya aku menuntut, tapi setelah apa yang kami lakukan terhadapmu apakah kami masih mempunyai hak ?
Leily, anakku..
Sampai saat ini Pra belum tahu mengenai anak kalian. Aku pulangkan hal itu kepadamu.. Walaupun aku ingin Pra mengetahuinya, mungkin kamu punya alasan untuk tidak melakukannya. Mungkin pada waktu kamu baca surat ini baik kamu dan Pra sudah punya keluarga sendiri-sendiri. Dan untuk kebaikan semua orang kamu memilih untuk melupakan semua masa lalu. Aku hormati itu.
Tapi, Leil, aku dan ayah Pra tahu kalau kami mempunyai cucu. Kami ingin meninggalkan sesuatu untuknya. Jangan kamu tolak pemberian kami. Dan mengenai Gotehan….Aku tahu tempat ini akan selalu mempunyai arti khusus bagimu. Kami memberikannya untukmu dan Pra.
Harapanku yang terakhir, Leil, kamu bisa memaafkan kami semua
Nenek anakmu.
Kucoba untuk mengevaluasi perasaanku setelah membaca surat ibu Pra. Tidak ada. Kosong. Hampa. Bahkan rasa benci, dendam ataupun sebercik kepuasan yang kuharapkan muncul, ternyata tidak muncul. Apakah aku sudah terbebas dari masa laluku?
Kuhembuskan nafas panjang dan berdiri termenung di depan jendela. Rumah peristirahatan di bukit seberang kelihatan cantik. Perkebunan ini akan segera berubah menjadi rumah-rumah peristirahatan cantik seperti itu, pikirku.
‘Rumah di seberang itu rumah mas Pra ?’ cerita ibu Warti, ‘Waktu kesini minggu lalu Mas Pra bilang kalau dia akan segera memboyong istri dan anaknya.’
‘Saya kira tanah ini akan dijual untuk dijadikan hotel,’ bisikku.
‘Mas Pra tidak akan mengijinkannya. Dia menyayangi tempat ini.’
‘Sekarang siapa yang tinggal di tempat itu?’ tanyaku
‘Tidak ada.’ sahut bu Warti.
Tiba-tiba muncul keinginanku untuk mengintip tempat itu. Aku ingin tahu tempat seperti apa yang disiapkan Pra untuk istri dan anaknya. Setelah itu aku akan memberikan bagian tanahku untuknya dan benar-benar berlalu dari hidupnya.
Pelan-pelan kudaki bukit untuk menuju ke rumah Peristirahatan Pra. Aku muncul di samping kiri kolam renang dan langsung berhadapan dengan rumpun anyelir yang sedang berbunga lebat. Aku meneruskan perjalanan menuju teras dengan dipan kayu dan bantal-bantal hiasnya. Tiba-tiba pintu teras terbuka lebar dan di depanku berdiri Pradipta. Pradiptaku dulu. Duniaku tiba-tiba berputar keras. Aku jatuh sempoyongan dan Pra menangkapku.
‘Jangan berani pingsan sekarang.’ ancam Pra sambil mendudukkanku di dipan. ‘Banyak yang harus kita bicarakan. Sesudah itu kamu boleh tidur sesukamu.’ lanjutnya. Pelan-pelan kubuka mataku. Pra duduk dekat sekali di sampingku sambil memandangku kuatir. Kulihat kerinduan di matanya. Pelan-pelan senyumnya terkuak.
‘Selamat datang kembali ke rumah, Leil. ‘ bisiknya. ‘Kamu pergi terlalu lama. Anggi dan aku sangat merindukanmu.’
‘Anggi ??’ aku tersentak kaget ‘Kamu tahu tentang Anggi ??’ Pra tersenyum sedih sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.
‘Secara kebetulan.’ ucap Pra. ‘Suatu hari adikku Rini bertemu Nita di Tunjungan Plaza sedang jalan-jalan dengan Anggi. Begitu melihat Anggi yang mirip aku, Rini segera menyadari kalau Anggi adalah anakku. Rini melaporkannya kepadaku. Waktu kutemui Nita membantah dan berkeras kalau Anggi adalah anak kandungnya. Setelah aku yakinkan dan berjanji kalau aku tidak akan mengambil Anggi tanpa persetujuanmu, barulah Nita menyerah. Aku juga meminta Nita untuk memberitahu kamu kalau aku sudah tahu semuanya. Melihat reasksimu tadi, aku rasa Nita tidak pernah memenuhi permintaanku. Kamu belum tahu kalau aku sudah mengetahui tentang Anggi dan Anggi sering menginap di rumahku’
‘Bagiamana reaksi istrimu ?’ tanyaku kuatir.
‘Istri ?’ ulang Pra diikuti tawanya yang nyaring. ‘Kamu pikir aku akan kawin dengan orang lain selain dirimu ?’
‘Bu Warti bilang kalau kamu akan segera memboyong istri dan anakmu kesini..’ ucapku.
‘Benar. Aku akan memboyong kamu dan Anggi kesini, Leil.’ bisiknya. ‘Kalau kamu mau.’
Tentu saja aku mau.
Posted in Short Stories
Tags: Cerpen, Femina, Fiction, Fiksi, Gotehan, Jombang, Laily Lanisy
Tentang Tami: Tembang Terakhir
Posted by Laily Lanisy
Adegan NCIS lagi tegang-tegangnya, ketika wajah Jethro Gibbs terhalang oleh munculnya pesan singkat Santi di layar TV-ku. Agar pesan dan telpon dari pelangganku tidak terlewatkan selagi aku terlena nonton TV, aku sengaja mengkaitkan telpon selulerku ke pesawat TV. Akibatnya ya seperti ini. Bukan hanya sms dari pelangganku saja yang sering mengganggu kenikmatanku menonton, tapi juga sms-sms dari teman yang tidak mendatangkan bisnis seperti sms Santi ini.
JANGAN LUPA PERTUNJUKAN MEGAN MALAM INI !!!!!!!! AJAK CLAY JUGA…. AKU SUDAH SIAPKAN MAKANAN TIDAK PEDAS UNTUKNYA !!!!!!!
Tulisannya persis seperti itu. Dengan huruf besar semua dan dengan belasan tanda seru, seolah untuk menekankan betapa pentingnya pertunjukan Megan ini untuk dirinya. Kalau sampai aku tidak muncul, dia akan murka sekali.
Mark Harmon seketika kehilangan daya tariknya. Aku bergegas ke kamar untuk berganti pakaian yang lebih tebal. Udara di luar lumayan dingin dan untuk menuju ke rumah Santi di Port Orchard aku harus naik feri dulu dari Seattle ke Bremerton selama satu jam dilanjut dengan naik mobil selama kurang lebih dua puluh menit. Sekarang sudah jam lima lewat. Mudah-mudahan aku aku bisa naik feri yang enam sore. Aku harus buru-buru. Tidak ada waktu untuk menghubungi Clay. Kedua-duanya akan aku lakukan nanti di atas feri saja.
Kukeluarkan Mini Cooperku dari garasi. Untung kemarin aku sempat mengisi bensin, jadi aku bisa langsung ke terminal feri tanpa harus mampir di pompa bensin terlebih dahulu. Mobil miniku masuk di terminal feri pada detik-detik teakhir. Telat semenit saja, aku harus menunggu feri berikutnya satu jam lagi dan pertunjukan Megan sudah pasti akan terlewatkan. Megan, anak Santi dan Greg, dari umur belia sudah belajar memainkan harpa. Di usianya yang sekarang, 15 tahun, dia sudah piawai memainkan dawai. Sesekali ibunya mengundang teman-teman dekatnya untuk makan malam dan Megan akan memainkan dua atau tiga komposisi.
Setelah memarkir mobilku, yang tentu saja terletak di bagian paling belakang feri, aku segera naik ke lantai atas, membeli segelas kopi dan menuju ke anjungan kapal bagian belakang. Pada bulan Februari seperti ini, tidak ada seorang pun yang beminat untuk duduk di tempat terbuka. Jadi seluruh anjungan belakang menjadi milikku.
Perlahan dan pasti, MV Sealth, feri yang kutumpangi mulai meninggalkan sandaran dan berlayar menjauhi Seattle, yang mulai memamerkan kerlap-kerlip lampu malamnya. Bangunan-bangunan tinggi di Seattle yang kalau siang hari kelihatan gagah dan angkuh berubah menjadi romantis di senja hari. Di bagian paling kiri, terisolasi dari bangunan-bangunan tinggi lainnya, menjulang bangunan favoritku, Space Needle, yang di usianya yang ke 50 tahun masih tetap saja kelihatan kontemporer dan mampu bersaing dengan bangunan-bangunan lainnya.
Kucoba menelpon Clay. Seperti biasa, tidak peduli sesibuk apapun, pada dering yang kedua dia menjawab telponku.
‘Hi, hon, what’s up?’ sapanya antusias
‘Pertunjukan Megan ternyata malam ini, Clay,’ ucapku. Lebih dari dua minggu lalu, Santi sudah mengedarkan undangannya lewat sms dan aku benar-benar lupa.
‘Aku masih ada dua pasien, Tam. Kamu mau menunggu aku atau kamu mau berangkat duluan nanti aku susul?’ tanya Clay. Aku yakin dia pasti masih sangat sibuk. Aku tidak ingin mengganggunya.
‘Aku sudah ada di atas feri, Clay,’ sahutku. ‘Lagi pula kamu tidak harus datang. Nanti kupamitkan ke Santi kalau kamu masih ada pasien dan kubawakan lemper buatannya,’ janjiku. Bule satu ini demen sekali lemper isi ayam. Apalagi buatan Santi.
‘Kamu yakin …
‘Sangat yakin.’
‘OK, hati-hati nyetirnya. Jalanan licin kalau musim dingin seperti ini.’
‘Ya, kek…,’ sahutku seperti biasa kalau dia sudah mulai dengan nasehat-nasehatnya.
Setelah memasukkan telponku ke dalam tas, aku mulai menikmati indahnya Puget Sound, perairan di depan kota Seattle di saat matahari mulai tenggelam. Karena bentuknya teluk, perairan disini sangat tenang. Dari kejauhan menjulang deretan pegunungan Olympic yang berselimutkan salju. Di kiri dan kananku berderet pulau-pulau kecil yang nampak kabur terhalang kabut. Sesekali ada pancaran cahaya lampu dari pulau yang menyeruak menembus kabut.
Keheningan Puget Sound tiba-tiba terkoyak oleh derit pintu yang terbuka. Seorang pemuda keluar dan sontak jantungku berhenti berdetak. Di depanku berdiri Bara. Bara dari masa dua puluh tahun silam. Baraku yang masih berusia remaja. Kugelengkan kepalaku dengan keras untuk memastikan kalau aku tidak sedang bermimpi. Ada yang salah dengan logikaku.. Remaja di depanku paling banter berusia tujuh belas tahun. Sementara Baraku sudah menjelang usia 40 tahun. Mustahil dia Bara. Kecuali Bara sudah berubah menjadi Edward Cullen dengan keabadian remajanya.
Pemuda di depanku mengembangkan senyumnya. Senyuman khas Bara. Bagaimana mungkin ada seseorang yang begitu mirip Bara. Anak Barakah dia?
‘Indonesia or Filipino?’ tanyaku membuka percakapan, walaupun seribu persen aku yakin kalau dia anak Indonesia dan mempunyai hubungan erat dengan Bara.
‘Indonesia,’ jawabnya hangat dan ramah.
‘Mau ke rumah tante Santi di Port Orchard?’ tebakku
‘Iya. Tante juga mau kesana?’ sahutnya sambil bersandar di pagar pengaman di depanku. Kuanggukkan kepalaku ‘Ibu saya teman kuliah tante Santi. Bunda minta saya untuk datang ke pertunjukan Megan,’ remaja itu menjelaskan. Dia menjelaskan dengan bahasa Indonesia yang lancar, namun aku bisa menangkap kalau bahasa Indonesia bukan bahasa pertamanya. Anak ini besar atau lahir di Amerika.
‘Teman tante Santi di Bloomington Indiana?’ tanyaku menyelidik Tiba-tiba muncul keinginanku untuk mengetahui semua tentang anak ini. Barangkali dengan mengetahui tentang dia, aku bisa mengetahui ihwal Bara.
Tanpa ada peringatan terlebih dahulu, sekonyong-konyong anganku melintas balik ke hampir 20 tahun silam. Balik ke kampus Bulaksumur, Yogya. Balik ke masa remajaku yang penuh dengan kenangan manis yang sekaligus getir. Umurku waktu itu baru 17 tahun, mahasiswa baru yang jatuh cinta kepada kakak kelasnya, Bara. Betapa indahnya cinta remaja. Betapa tidak adilnya kehidupan.
Di saat dunia luas mulai terbuka di depan mataku, di saat aku begitu mencintai kehidupan dan siap mengepakkan sayap untuk menggapai cita-cita, Leukimia mengincar nyawaku dengan kejam. Aku yang pemain inti basket di universitas, yang doyan naik turun gunung, yang nilai ujian terendahnya B+, yang punya cowok ganteng bernama Bara, harus berperang melawan penyakit yang menggerogoti tubuhku.
Pengobatan demi pengobatan kujalani dengan sabar. Dari chemotherapy yang merontokkan semua rambutku hingga pengobatan alternatif yang tidak jelas juntrungannya. Di sela-sela pengobatan itu, jalinan cintaku dengan Bara terajut dengan indah dan kokoh. Bara adalah alasan utamaku untuk mempertahankan hidup yang semakin hari semakin berat. Bara adalah batu cadasku di saat aku hampir putus asa. Di saat seluruh tubuhku bengkak dan penuh dengan benjolan, Bara masih menganggapku gadis tercantik dan dengan bangganya memamerkanku ke seluruh dunia. Bara adalah cahaya yang menerangi kelamnya masa depanku.
Namun, harapan hidupku semakin hari semakin tipis, hingga tidak ada lagi yang tersisa. Melihat Bara yang tadinya menguatkanku berubah menjadi beban. Setiap kali penyakitku kumat kulihat penderitaan hebat di mata Bara. Dia yang pada mulainya tenang, mulai sering panik. Dia mulai menelantarkan masa depannya. Dia lebih sering mangkir dari kampus dan beredar di rumah sakit menemaniku.
Di penghujung perjuanganku, di saat tubuhku menolak segala jenis pengobatan, datang undangan dari Universitas Washington di Seattle untuk menjadi salan satu pasien uji coba pengobatan dengan sistem stem-cell. Semua biaya mereka tanggung. Karena sudah tidak ada alternatif lain, akhirnya berangkatlah aku ke Seatlle.
Bara masih sempat mengantarku di Bandara Soetta. Sebelum keberangkatku, aku memaksanya berjanji untuk melupakanku dan melanjutkan hidupnya. Aku tidak mempunyai apa-apa yang bisa aku janjikan untuknya. Sama sekali tidak ada. Jauh di dalam lubuk hatiku, aku merasa tidak mempunyai peluang di Seattle. Aku pergi untuk tidak kembali
Ternyata, pengobatan di Seattle menunjukkan hasil yang berbeda. Setelah lebih dari tiga tahun aku dinyatakan bersih dari Leukimia. Aku mendapatkan masa depanku kembali. Aku punya waktu untuk bercinta lagi. Aku bisa menghubungi Bara kembali.
‘Jangan,’ cegah abangku Tommy saat kuungkapkan keinginanku untuk menghubungi Bara. ‘Bara sudah melanjutkan hidupnya. Dia sedang mengambil S2 dan sebentar lagi akan kawin dengan gadis lain. Kamu sendiri yang menginginkn itu. Jangan kamu ganggu dia.’
Aku pun maklum. Inilah harga yang harus kubayar untuk kesembuhanku. Aku mendapatkan hidupku tapi aku harus melepaskan cintaku. Merasa tidak ada lagi alasan untuk balik ke Yogya, akupun memutuskan untuk tinggal di Amerika. Walaupun pahit dan menyesakkan dada, kukubur dalam-dalam kenanganku bersama Bara.
‘Tante ..’ panggilan anak itu menyadarkanku dan menarikku kembali ke masa kini.
‘Maaf, kamu mengingatkanku pada seseorang,’ ucapku. ‘Pertanyaannya tadi apa?’ lanjutku. Anak itu tertawa. Gelak tawanya persis seperti gelak tawa Bara kala menertawakan kekonyolanku.
‘Saya tadi bilang ke tante, nama saya Tommy, tante siapa?’ ucapnya sabar. Untuk beberapa detik aku diam terpana. Bara menamakan anaknya Tommy, seperti nama kakakku? Apakah kalau anaknya perempuan dia akan menamakanya Tami?
‘Nama tante Tami.’ ucapku. Pemuda di depanku yang ternyata bernama Tommy tertawa membahana. Jika tadi aku belum yakin kalau dia anak Bara, kini aku yakin sekali. Seyakin matahari terbit dari timur setiap paginya.
‘Nama kita mirip ya?’ olokku.
‘Bukan itu saja, tante,’ jawab Tommy. ‘Pacar ayah saya dulu namanya juga Tami, makanya saya dinamakan Tommy. Dari nama pacar ayah,’ lanjut Tommy. Aku terkesima. Bara sama sekali tidak merahasiaka masa lalunya.
‘Bundamu tidak keberatan kamu dinamakan Tommy?’ tanyaku menyelidik. Tommy terdiam beberapa saat.
‘Ayah saya orangnya sangat keras dan kaku, Tante,’ ucapnya kemudian. ‘Bunda memilih untuk mengalah. Bunda selalu mengalah. Mereka pernah mengalami masa-masa sulit. Sekarang sudah jauh lebih baik,’ sambungnya ringan. Dia bercerita seolah aku adalah tantenya yang sudah dia kenal sejak lahir.
‘Jangan-jangan tante adalan Tami, cewek ayahmu dulu,’ pancingku juga berlagak ringan.
‘Tidak mungkin, Tante,’ jawab Tommy cepat. ‘Taminya ayah sudah meninggal sebelum ayah ketemu Bunda.’ Aku terdiam. Hatiku seketika membeku. Ternyata bagi Bara aku sudah mati. Untung saat itu peluit panjang sudah dibunyikan, pertanda kapal mulai merapat di Bremerton. Karena Tommy tidak membawa mobil, kutawarkan kepadanya untuk ikut bersamaku.
Selama dua puluh menit perjalanan dari Brementon ke Port Orchard, aku mencoba menggali informasi dari Tommy. Mencoba memahami apa yang membuat Bara yang dulu kukenal sangat lembut dan penuh pengertian berubah menjadi kaku dan berkeras untuk menamakan anaknya Tommy, tanpa mempertimbangkan perasaan istrinya.
Sudah banyak mobil yang parkir di halaman rumah Santi ketika kami sampai di sana. Rumah Santi letaknya terpencil, jauh dari tetangga. Di kiri dan kanan bangunan utamanya yang besar dipenuhi dengan hutan pinus dan halaman belakangnya adalah pantai pribadi. Kalau musim panas, kami sering mencari kerang untuk dimasak bersama. Greg, suami Santi adalah seorang dokter bedah jantung, dan bekerja di rumah sakit yang sama dengan Clay. Clay lah yang memerkenalkan aku dengan Santi dan Greg, bukan sebaliknya.
Santi sudah menunggu di depan pintu ketika kami datang. Sama sekali di luar kebiasaanya. Sambil memelukku dia berkata ke arah Tommy.
‘Ayah dan Bundamu ada di kamar tamu atas, Tom.’
Aku membelalakkan mataku, tidak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut Santi. Tommy segera menghambur ke dalam.
‘Kamu tahu siapa ayah Tommy?’ tanya Santi berbisik. Kuanggukkan kepalaku.
‘Bara ada disini?’ tanyaku tidak percaya. Santi menggangguk, menggamit lenganku dan menggandengku menjauhi rumah menuju pantai. Lampu-lampu di sepanjang jalan setapak menuju ke pantai sudah menyala dengan terang.
‘Dan kamu tidak memberitahuku kalau dia ada disini? Kukira kamu temanku, San,’ protesku.
‘Aku temanmu, Tam, percayalah. ‘Bara memintaku untuk tidak memberitahumu. Kalau kamu tahu kamu pasti tidak akan datang,’
‘Tentu saja aku tidak akan datang,’ sergahku. ‘Kamu sadar enggak sih, San, betapa canggungnya pertemuan ini? Lagian dari mana Bara bisa tahu tentang keberadaanku?’
‘Dari Facebook,’ jawab Santi singkat
‘Aku tidak punya akun Facebook, San’ bantahku sengit.
‘Dari akunku. Mita mengunggah beberapa foto perkawinannya. Ada foto kita berdua disana. Bara melihat foto itu dan menanyakan tentang kamu. Karena aku tidak tahu kalau aku harus merahasiakan keberadaanmu, ya aku jawab apa adanya,’ Santi menjelaskan. ‘Bara dan istrinya, Maya ingin bertemu denganmu. Aku katakan kepada mereka kalau kamu akan datang pada acara Megan ini. Dan mereka sengaja datang untuk menemuimu.’
‘Mereka datang jauh-jauh dari Indonesia?’
‘Mereka tinggal di Portland, Tam. Setelah lulus dari Indiana mereka kerja di Portland.’ Aku tertegun. Tidak menyangka kalau selama ini Bara berada hanya tiga jam dari tempat tinggalku.
‘Apa yang kamu ketahui tentang aku dan Bara?’ selidikku.
‘Banyak,’ jawab Santi. ‘Aku roommate Maya dari tingkat satu hingga lulus, Tam. Aku menjadi saksi perubahan dramatis Maya sejak kemunculan Bara di Bloomington. Dia jungkir balik mencoba menggapai cinta Bara yang sudah habis kikis untukmu. Aku kasihan melihat dia bersaing dengan hantumu. Seingatku Bara pernah bilang kalau hatinya sudah mati bersamaan dengan kematian gadisnya. Aku dan Maya mengira kalau kamu benar-benar sudah mati, Tam. Belasan tahun aku mengenalmu dan aku tidak pernah tahu kalau kamu adalah gadis Bara’
‘Bagi Bara aku sudah lama mati, San,’ bisikku.
‘Omong kosong,’ bantah Santi sengit. ‘Bara tidak pernah bisa melupakanmu. Di matanya kamu sempurna sehingga Maya harus berjuang keras untuk bersaing dengan bayanganmu. Dan kurasa kamupun demikian juga. Bara adalah tolok ukurmu. Dia juga yang membuatmu menolak lamaran Clay kan?’
‘Clay tidak pernah melamarku..’ bantahku. Tiba-tiba aku membutuhkan Clay di berada di sampingku saat ini juga. Membutuhkan dia untuk mengatakan apa yang harus aku lakukan dalam menghadapi Bara yang tiba-tiba berada dalam jangkauanku. Tanpa aku sadari ternyata selama ini aku banyak mengandalkan Clay dalam memutuskan sesuatu.
‘Untung dia tidak melamarmu,’ sahut Santi. ‘Kalau sampai dia melamarmu, kamu akan terbirit-birit meninggalkannya. Dan kamu akan menjadi wanita tua yang kesepian tanpa teman sekaligus kekasih,’ ucap Santi sambil melihat ke arah rumah.
‘Temuilah mereka, Tam,’ lanjut Santi. ‘Sudah saatnya kalian menghadapi hantu masa lalu kalian dan melangkah maju. Yuk masuk, sudah saatnya untuk makan malam..’ ajaknya mengalihkan pembicaraan.
‘Kamu masuklah dulu, San. Aku butuh waktu sebentar untuk menyendiri,’ ucapku. Santi memandangku sejenak kemudian menganggukkam kepalanya. Setelah berpesan agar aku segera menyusulnya dia meninggalkanku.
Aku duduk mematung di atas batang pohon yang tumbang terbawa arus. Memandang ke depan. Ke gelapnya malam yang menggelantung di atas laut yang mendesah halus. Cepat atau lambat aku harus menemui Bara dan istrinya. Pada saat aku siap untuk beranjak dan menuju ke rumah utama, aku melihat sesosok bayangan yang berjalan dengan cepat dan pasti ke arahku. Aku berdiri dan menanti dengan cemas. Aku kenal betul pemilik bayangan itu. Seribu tahun dari sekarang pun aku masih akan tetap mengenalinya.
‘Tami…?’ bisiknya ragu. Hanya sekejab. Sekejab kemudian dia sudah merengkuhku ke dalam pelukannya yang erat. Erat sekali hingga aku nyaris tidak bisa bernafas. Dua puluh tahun yang memisahkan kami sirna sudah. Tanpa bekas. Kami kembali ke masa lalu. Ke masa dimana pelukan Bara mampu menghilangkan semua ketakutan di dalam diriku. Tidak ada kata-kata yang terucap, takut kalau kata-kata justru akan membuyarkan momen yang indah ini. Lama kami berada dalam keadaan seperti itu. Hingga sebutir air mata Bara bergulir menimpa pipiku. Aku tersadar dan melepaskan diri dari pelukan Bara, mengambil jarak, namun masih tetap menggenggam kedua tangannya.
‘Aku tidak menyangka kita bisa bertemu lagi, Bar,’ kataku dengan susah payah sambil menghapus air mata dari pipinya.
‘Mereka semua membohongiku, Tam,’ ucapnya serak. ‘Mereka membohongiku. Membohongiku,’ ucapnya berkali-kali.
‘Siapa yang membohongimu?’ tanyaku bingung.
‘Semuanya … Ayahmu, ibumu. kakakmu Tommy dan istrinya, Oki. Kira-kira dua bulan setelah keberangkatanmu ke Amerika, mereka bilang kalau pengobatanmu gagal. Mereka bilang kalau kamu sudah meninggal.’
‘Mungkin kamu salah mengerti ..’
‘Tidak, Tam,’ sanggah Bara. ‘Itu yang mereka katakan. Aku tidak percaya ketika mereka bilang kalau kamu sudah meninggal. Aku masih merasakan keberadaanmu. Aku masih merasakan detak jantungmu. Tapi mereka terus meyakinkanku. Mereka bahkan mengadakan tahlilan dan peringatan 40 harimu dengan mengundang anak-anak panti asuhan. Mengapa kamu tidak berusaha untuk menghubungiku, Tam?’
‘Pengobatanku sangat berat, Bar.’ kataku. ‘Mempertahankan hidupku saja sulit. Aku tidak punya daya untuk memikirkan hal lainnya. Aku tidak tahu mengapa mereka membohongimu. Tapi aku yakin mereka melakukan itu karena mereka menyayangimu, Bar. Kalau aku di posisi mereka, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Aku pasti tidak akan rela melihat kamu menyia-nyiakan hidupmu, menungguku tanpa ada kepastian. Sekarang lihatlah, kamu punya Maya dan Tommy. Oh ya, aku ketemu Tommy di atas feri, dia benar-benar mirip kamu.’
Wajah Bara yang tadinya tegang seketika menjadi santai mendengar nama anaknya kusebut. Dia berusaha untuk tersenyum.
‘Untuk beberapa bulan setelah kepergianmu, aku depresi berat. Aku sangat menderita. Aku gila, Tam. Aku masih merasakan kehadiranmu. Satu-satunya jalan untuk mengabaikan kehadiranmu hanya belajar dan belajar. Kuliah kukebut dan aku lulus dengan predikat mahasiswa terbaik. Aku tidak bahagia, Tam. Aku juga tidak bahagia ketika mendapat beasiswa penuh tanpa ikatan ke Bloomington. Untung disana aku ketemu Maya. Dia yang menyelamatkan hidupku. Dia yang mengajariku untuk tersenyum lagi dan menunjukkan kepadaku kalau hidup ini masih layak untuk dinikmati,’ tutur Bara. Untuk pertama kalinya, dalam hatiku, aku berterimakasih kepada Maya yang pantang putus asa dalam mencintai Bara.
‘Kamu cinta Maya, Bar?’ tanyaku terlepas begitu saja. Tidak pada tempatnya bagiku untuk menanyakan hal itu. Aku sama sekali tidak berhak untuk menanyakannya. Bara tersenyum.
‘Awalnya tidak, Tam,’ akunya. ‘Hatiku terlampau hampa untuk mencinta. Tapi aku tahu Maya wanita baik, wanita yang sangat baik. Aku tahu dia mencintaiku tanpa syarat. Mencintai aku yang sudah remuk dan tidak lagi memiliki hati. Aku tahu aku tidak akan menemukan wanita sebaik dia. Setelah selesai kuliah, terdorong naluriku yang kuat kulamar dia untuk jadi istriku. Aku tidak tahu kapan aku mulai mencintainya. Yang jelas sejak bersamanya, memikirkanmu tidak lagi menyesakkan dadaku. Kamu menjadi kenangan yang indah, sementara Maya adalah cintaku yang nyata,’ lanjut Bara sepenuh hati. Kupeluk dia kembali dan kudaratkan kecupan di pipi kiri dan kanannya untuk menghapus segala kepedihan yang pernah dia derita gara-gara kepergianku.
‘Aku bahagia untukmu, Bar. Benar-benar bahagia untuk kamu, Maya dan Tommy. Maafkan aku bila aku pernah menjadi sumber penderitaanmu.’
‘Bagaimana dengan dirimu, Tam? Apakah kamu bahagia?’ tanya Bara konsern. Bahagiakah aku?
‘Aku tidak tahu, Bar,’ sahutku jujur. ‘Umurku 38 tahun. Masih hidup. Sehat. Punya usaha disain perhiasan sendiri. Punya rumah yang baru lunas kalau umurku 55 tahun nanti. Punya teman setia yang bernama Clay, yang kata Santi tidak berani melamarku karena takut aku akan lari terbirit-birit meninggalkannya… Mungkin kalau disimpulkan, ya aku cukup bahagia,’ Bara tersenyum mendengar penuturan singkatku yang sudah mencakup semua yang ingin dia ketahui.
‘Apakah kamu mencintai Clay?’ tanya Bara diluar dugaan. Kalau aku boleh menanyakan apakah dia mencintai Maya, tentunya dia pun boleh menanyakan hal yang sama kepadaku.
‘Mungkin seperti kamu, Bar, aku agak lamban untuk menyadarinya,’ sahutku. Clay masih dokter intern ketika aku mulai menjalani pengobatan. Dokter termuda di dalam tim dokter yang menanganiku, sehingga lebih mudah bagiku untuk berkomunikasi dengannya ketimbang dengan dokter-dokter lainnya. Setelah aku sembuh pun, Clay selalu berada di dekatku. Dia yang membantuku untuk kembali kuliah. Membantuku mendirikan usaha sendiri setelah kuliahku selesai. Ketika rumah di sebelah rumah Clay dijual, Clay yang mendorongku untuk membelinya. Jadi secara fisik kami memang dekat. Sementara secara perasaan, aku tidak pernah menganalisanya.
‘Sebaiknya kita masuk ke rumah, Bar. Pertunjukan Megan pasti sudah dimulai dan aku ingin ketemu Maya,’ ajakku mengalihkan pembicaraan. Bara setuju. Berdua kami mulai melangkah menuju ke rumah utama. Lengan kanan Bara memeluk pundakku. Kebiasaan lama… berjaga kalau-kalau aku mendadak pingsan selagi berjalan. Aku menoleh ke arahnya dan tersenyum.
‘Aku sudah sehat sekarang, Bar. Kamu tidak perlu menjagaku lagi,’ bisikku. Dia tertawa pelan, tapi tetap memelukku. Dia masih juga memelukku ketika kami memasuki ruang keluarga yang luasnya hampir seluas Balairung, kampus Bulaksumur. Kutebarkan pandangku keseluruh ruangan. Megan sudah siap dengan harpanya dan sebagian besar tamu sudah duduk manis membentuk setengah lingkaran di depannya. Beberapa masih berdiri di dekat meja makan. Megan yang pertama menyadari kehadiran kami.
‘Tante Tami, mau mengiringiku dengan piano?’ Megan menawarkan ke arahku. Semua menoleh ke arah kami. Termasuk seorang wanita cantik yang berdiri di samping Santi di dekat meja makan, yang memandangku dengan pandangan yang sulit untuk diartikan. Inilah Maya. Istri Bara dan bunda Tommy. Aku tersenyum ke arahnya. Melalui senyumku ingin kusampaikan terima kasihku karena telah menyelamatkan Bara.
‘Tidak malam ini, Meg,’ ucapku ke arah Megan sambil melepaskan diri dari pelukan Bara dan menghampiri Maya. Bara berjalan tepat di belakangku. Belum sempat Bara memperkenalkan aku dengan Maya. Aku sudah memeluk Maya dan mencium pipi kirinya.
‘Bunda, ini Tami,’ kata Bara. ‘Tam, ini Maya istriku.’
‘Aku tahu!!’ Aku dan Maya menyahut serentak. Dengan sahutan itu, kekakuan di antara kami pun mencair. Hilang tanpa bekas.
‘Kukira kalian sudah berada di atas feri dan melarikan diri berdua,’ seloroh Maya.
‘Rencananya seperti itu,’ sahut Bara. ‘Ternyata Tami lebih senang melarikan diri dengan orang lain’
‘Makasih, Tam,’ sahut Maya. ‘Wah, aku harus lebih waspada sekarang. Sebagai hantu saja, Tami sudah saingan berat, apalagi segar bugar kayak remaja gini,’ lanjutnya ringan. Baru saja aku mau membalas ucapan Maya, Megan sudah mulai memainkan jari-jari lentiknya. Aku bergegas mencari tempat duduk yang kosong. Kulihat sofa satu dudukan di bawah lukisan Thomas Kinkade. Aku menuju ke sana. Dengan sudut mataku, aku melihat Bara dan Maya mengambil tempat duduk berdampingan, agak jauh dari tempatku. Sebelum larut dalam permainan Megan aku panjatkan syukur kepada Tuhan karena telah menyatukan Bara dan Maya. Mereka berdua adalah pasangan yang sangat serasi.
Ketika Megan mulai memainkan komposisi kedua, tiba-tiba ada yang duduk di lengan sofaku. Aku menoleh dan mendongakkan wajahku. Clay mengembangkan senyum manisnya. Belum pernah aku segembira ini melihat kehadirannya. Aku bergeser dan mempersilahkan dia untuk berbagi sofa denganku.
‘Kukira kamu tidak datang, Clay,’ bisikku.
‘Dan membiarkanmu menemui mantan pacarmu seorang diri? Not a chance,’ jawab Clay tepat di telingaku. Aku tersenyum dan otomatis menoleh ke arah Bara dan Maya yang ternyata sedang memandang ke arah kami. ‘Clay’ kuucapkan nama Clay tanpa suara ke arah Bara dan Maya. Bara menganggukkan kepalanya sambil mengacungkan jempol tangan kanannya seakan memberikan persetujuannya. Aku bernafas lega. Kusandarkan kepalaku ke dada Clay. Kutemukan kedamaian disana.
‘Pertemuanku dengan Bara adalah sebuah encore, Clay. Tembang terakhir sebelum pertunjukan usai. Mulai sekarang, hanya ada kita berdua. Tidak ada lagi hantu masa lalu yang berkeliaran di antara kita,’ janjiku.
Austin, February 2014
Have a Romantic Valentine, Friend…
Posted in Short Stories, Stories
Tags: Cerita Valentine, Cerpen, Indonesia, Short Stories, Stories, Valentine, Valentine Stories
Nafas Muda Kota Yogya
Posted by Laily Lanisy
Untuk ketiga kalinya Dina harus menghentikan sepeda motornya karena traffic light menyala merah. Sekejab dia melirik pada pengendara trail yang berhenti di sampingnya. Pemuda berpakaian urakan yang tadi juga berhenti di traffic light kedua di simpang tiga Gondomanan. Pemuda itu menggerak-gerakkan tangan kanannya yang berada di stang gas sehingga bunyi mesinnya meraung-raung. Dina menoleh dan menatap tak senang ke arahnya. Pemuda itu balas menatap Dina dan mengedipkan sebelah matanya sambil tersenyum lebar hingga ujung bibirnya hampir menyentuh daun telinga. Dengan cepat Dina membuang muka. Pemuda itu tertawa mengejek.
‘Pemuda sinting!’ maki Dina dalam hati. Pemuda itu makin mempercepat frekuensi gerakan tangannya sambil tangannya yang satunya lagi menekan knob klakson berkali-kali sehingga menimbulkan suara yang membisingkan telinga dan memusingkan kepala.
‘Yakis kamu!’ teriak Dina dongkol. Yakis dalam bahasa Ternate berarti monyet. Dina mendapatkan kata itu dari Yance yang berasal dari Maluku Utara.
‘Apa?’ tanya pemuda itu lantang berusaha mengalahkan bunyi mesin motornya sendiri. Dina tak sudi menjawab. Pemuda itu mengecilkan gasnya dan bertanya lagi.
‘Ya … kis,’ jawab dina.
‘Apa itu?’ tanya si pemuda bingung.
‘Ya kamu itu,’ jawab Dina acuh.
‘Aku tidak mengerti,’ kata pemuda itu dengan polos sehingga kesan sok jagoan yang baru saja ditunjukkannya luntur. Dina menahan tawa.
‘Makanya sekolah yang benar biar mengerti,’ kata dina sambil mengalihkan perhatiannya. Kali ini dia menatap mobil sport berwarna biru metallic yang berhenti tepat di depannya. Begitu mulus dan …
‘Hei itu ulang tahunku …itu inisialku!!!’ cetusnya tidak sadar ketika tanpa disengaja matanya nyasar ke plat nomer mobil itu… AB-2808-DR. Kemudian dia menjulurkan kepalanya ingin melihat wajah yang ada di dalam mobil. Tidak berhasil.
‘Enggak sekeren mobilnya,’ komentar si pemuda ’Yakis’ melihat ulah Dina.
‘Enggak minta pendapatmu,’ bentak Dina. Untung lampu lalu lintas segera berganti hijau hingga dina dapat melejitkan sepeda motornya.
Di depan Hotel Melia Purosani, Dina dapat mendahului mobil metallic yang tadi berhenti di depannya. Ketika tepat berada di samping kanan mobil itu, Dina melongok untuk melihat pengemudinya. Tetapi begitu melihat wajahnya langsung dia tancap gas.
‘Lagi-lagi Tionghoa. Tak ada orang pribumi asli yang dapat naik sedan semewah itu,’ pikirnya kecewa. Di belokan Pasar Kembang ganti mobil tadi yang mendahului Dina. Dina berpikir sejenak sebelum mempercepat kendaraannya. Tepat di bawah Kretek Kewek Dina dapat berada di samping mobil itu. Tapi … Entah disengaja atau tidak pemuda yang berada di dalam mobil itu meludah. Ujung rok Dina terkena sedikit. Langsung Dina memaki. Semua kata-kata kotor yang pernah didengar dan dibacanya meluncur dari mulutnya sederas aliran Kali Code. Sayang sang pengemudi mobil biru metallic enggak bisa mendengarnya. Itu membuat Dina semakin dongkol.
‘China yakis! Tak tahu aturan, enggak pernah diajar adat,’ gerutunya sambil meminggirkan motornya. Sesudah mematikan mesin dia mengambil tissue dari dalam tasnya dan mulai membersihkan rok yang terkena percikan air liur. Sebenarnya yang terkena hanya sedikit saja, tetapi berhubung hatinya panas maka rok yang dikenakannya seakan benar-benar kotor dan bau. Selagi dia berpikir apa yang akan dilakukannya kemudian, datang si pemuda ’Yakis’ dan berhenti di dekatnya.
‘Ada apa? Mogok ya?’ tanyanya penuh perhatian. Dina siap membentaknya dengan kata-kata pedas, tapi urung.
‘Ah enggak,’ jawab Dina manis. ’kamu ingat China gila yang tadi berhenti di depan kita?’ Dina merobah siasat.’Hmm … siapa tahu Yakis ini bisa diajak kompromi untuk menghajar si China keparat,’ pikir Dina dalam hati.
‘Yang mana?’ tanya si pemuda sambil mengernyitkan dahi.
‘Yang pakai mobil sport biru metallic mulus tadi.’
‘O iya. Kenapa?’
‘Nih lihat apa yang dilakukannya,’ kata Dina sambil menunjuk roknya yang sudah tak ada apa-apanya lagi. ’Ngeludahin aku, anak Indonesia asli,’ lanjut Dina.
‘Ah enggak disengaja barangkali,’ pemuda itu mengeluarkan pendapatnya.
‘Pasti disengaja,’ bantah Dina. ’China-China di sini semuanya memang begitu. Merasa diri kaya. Merasa diri penting karena dapat tinggal di sepanjang jalan-jalan penting. Mereka sukanya berlagu. Ih … sebel,’ omel Dina sambil menstater motornya.
‘Kurasa tidak semuanya begitu,’ pemuda itu berargumentasi.
‘Semuanya begitu. Kalau ada China yang baik itu namanya tidak normal. Anomali. Suatu perkecualian yang jarang terjadi. Kalau mereka suatu saat berbaik hati, pasti ada maksud yang disembunyikan.’ Dina menekankan setiap kata yang dianggapnya penting dan menjalankan sepeda motornya.
‘Kalau demikian kamu bersikap prejudis. Tidak baik seperti itu.’
‘Aku tak butuh nasihatmu. Kalau aku prejudis terhadap China itu adalah hakku,’ potong Dina sambil mengebutkan motornya. Si pemuda ikut-ikutan mengebutkan motor trailnya hingga selalu dapat menyamai kecepatan Dina.
‘Aku sudah sampai,’ kata Dina ketika mereka telah berada di depan sekolah Dina. Pemuda itu menghentikan sepeda motornya sementara Dina telah membelok masuk halaman sekolah.
‘Hei, sebentar!’ teriak pemuda itu. Dina menghentikan motornya dan menoleh.
‘Ada apa? “
‘Namamu siapa?’ tanya si Pemuda. Dina tertawa nyaring.
‘Namaku Yakis,’ teriak Dina sambil meneruskan perjalanan.
Ketika Dina memasuki kelasnya, semua temannya sudah berada di dalam kelas. Seperti biasanya jika ada pekerjaan rumah maka dapat dipastikan semua temannya akan datang lebih awal dan mengcopy pekerjaan rumah temannya yang mempunyai otak cemerlang. Kemudian Dina mendudukkan dirinya di samping Yance, gadis berkulit putih berambut panjang yang sedang asyik menulis.
‘Buram amat wajahmu. Ada problem?’ tanya Yance tanpa menoleh ke Dina.
‘Aku baru saja dihina seseorang. kamu mau menolongku?’ tanya dina. Yance menghentikan pekerjaannya, menatap dina serius.
‘Siapa yang menghinamu? Kuganyang dia,’ bisik Yance sambil menutup bukunya. Diam-diam Dina mengagumi temannya yang satu ini. Walaupun wajahnya tidak secantik teman-temannya yang lain tetapi rasa kesetia kawanan selangit.
‘Aku tidak tahu namanya. Aku tidak tahu rumahnya. Satu-satunya yang kuketahui dia orang China,’ jawab Dina. Kalau orang lain yang diajak bicara pasti akan mentertawakannya, tetapi berhubung yang diajak bicara Yance, yang mempunyai solidaritas setinggi gunung, maka dia tidak tertawa. Dia mengetuk-ngetuk kan ballpointnya di bangku sambil berpikir bagaimana mungkin seseorang yang belum dikenal Dina bisa melakukan penghinaan yang membuat wajah Dina buram seburam kaca di pagi hari.
‘Bagaimana itu bisa terjadi?’ tanya Yance setelah lama tak bisa membayangkan jalan cerita temannya. Kemudian Dina menceritakan semuanya dari awal lengkap dengan titik-komanya.
‘Kurangajar amat,’ geram Yance.’Orang kalau sudah jadi Maliong sering lupa asalnya. Tidak sadar rupanya dia dari mana dia dapat memperoleh kekayaannya,’ cerocos Yance. Tak disadari Yance telah menggunakan kata-kata yang tak di mengerti Dina.
‘Apa itu maliong?’ tanya Dina melupakan masalah pokoknya.
‘Milyuner, tolol,’ kata Yance. Dina tertawa.
‘Apakah kita akan mendiamkannya saja?’ tanya Dina.
‘Tentu saja tidak,’ tukas Yance. ’Dengar baik-baik Din. Nomer mobil itu sama dengan ulang tahunmu. Huruf belakangnya seperti inisial namamu. Berarti kita tahu nomor mobilnya. Nah, kita mulai dari situ.’
‘Apakah kita akan keliling kota untuk mencari mobil itu? Nyerah deh kalau aku kamu suruh melakukan hal itu. Tak sanggup,’ protes Dina.
‘Tentu saja tidak. Aku tidak segila itu,’ kata Yance.
‘Lalu?’ tanya Dina. Yance diam saja. Dia berpikir bagaimana mendapatkan cara yang tidak ’gila’ untuk memperoleh informasi tentang pemilik mobil berwarna metallic yang telah menghina temannya.
‘Ah Yong,’ teriak Yance akhirnya. ’Dia pasti tahu mobil-mobil mewah yang dimiliki orang-orang sebangsanya.’
‘Aku tak mau berhubungan dengan China lagi, tak terkecuali si Yong,’ kata dina.
‘Tak ada jalan lain, Din. Lagi pula Ah Yong orangnya baik, tidak semua China berhati jelek lho.’
‘Pokoknya aku enggak mau. Kalau kamu mau tanya, silakan.’
‘Oke, kamu tenang-tenang saja. Tahu beres,’ kata Yance sambil membuka bukunya kembali.
‘Keesokan harinya Yance telah mendapatkan semua informasi, baik yang diperlukan maupun yang tidak.
‘Ayo, Din,’ ajak Yance pada istirahat pertama. Kemudian mereka menuju ke sebuah bangku beton yang ada di bawah pohon karet yang berada di halaman tengah sekolah mereka. Sesudah duduk Yance mengeluarkan sesobek kertas kumal pembungkus rokok.
‘Mobil itu mobilnya babah Kwan Chee Wai,’ Yance mulai bercerita sambil membaca tulisan pada kertas yang ada di tangannya. ’Babah ini pemilik toko sepatu Lion. Itu lho yang di jalan Solo.’
‘Yan, orangnya masih muda. Paling banter dua tahun di atas kita,’ potong Dina.
‘Sabar dulu …’ kata Yance sambil melicinkan kertasnya. ’Dia punya tiga anak laki-laki. Satu kuliah di Sanata Dharma, satu lagi sekolah di De Britto dan yang terkecil sekolah di Budya Wacana.’ Yance berhenti sejenak untuk melihat reaksi Dina. Tapi wajah Dina begitu tenang tidak menunjukkan apa-apa.
‘Yang kuliah di Sadar namanya Kwan Kim Fui, biasa di panggil Kim. Kurasa orang inilah yang meludahimu. Orangnya memang agak sombong,’ lanjut Yance. Dina memandang Yance kagum.
‘Bagaimana manusia satu ini bisa memperoleh data selengkap itu. Pantas deh untuk petugas sensus,’ pikir Dina.
‘Anak yang kedua. Aduh ma … Dia paling ganteng di antara semuanya. Wajahnya mirip Tou Ming She-nya Meteor Garden, enggak dhing mirip Adam Jordan. Enggak tampak deh kalau dia itu orang China.’
‘Biar. Nah teruskan,’ potong Dina.
‘Di De Britto dia juara umum. Jurusan IPA kelas tiga.’
‘Kenapa sih kamu kok jadi antusias banget nyeritakan yang ini. Aku enggak butuh dia aku cuma butuh yang, siapa tadi … Kim … Kim.’
‘Oke …’ Yance menurut, ’Kim Fui… Nah, si Kim Fui ini punya adik sekolah di De ..’
‘Setan kamu!’ teriak Dina dongkol. Yance tertawa ngakak.
‘ kamu ingin dengar tentang adiknya yang bungsu?’
‘Enggak.’
‘Pacar Kim Fui ini si Bimbi. Ingat enggak kamu sama ratu Disco Colombo yang cantik nan jelita itu? Namanya yang sebenarnya adalah Tan Beng Choo,’ kata Yance. Dina tertawa senang. Yance mau menambah keterangannya lagi tapi keburu distop Dina.
‘Kurasa cukup lengkap. Kamu kuangkat jadi detektifku,’ kata Dina sambil bangkit setelah terlebih dahulu menyerobot kertas kumal Yance. Yance tersenyum puas. ’Sekarang ayo ikut aku. Kita jalankan misi kita,’ lanjut Dina.
‘Apa yang akan kamu lakukan? kamu tidak akan ngawur kan? “
‘Sejak kapan orang yang namanya Yance kenal takut?’ tantang Dina. Dan yance mengikuti langkah Dina. Mereka keluar menuju kantor telpon yang berada di sebelah timur sekolah mereka.
Seorang gadis berseragam Telkom menegur Dina ketika Dina dan Yance memasuki Kantor itu.
‘Eh, mbak Yanti, mau pinjam telpon, mbak,’ kata Dina manis.
‘Emang enggak bawa HP?’ tanya gadis yang dipanggil Yanti itu.
‘Kelasku lagi dihukum enggak ada yang boleh bawa HP ke sekolah minggu ini ..’ sahut Dina mulus. Untuk yang mau Dina lakukan ini dia harus menggunakan telpon umum. Dia tidak mau telponnya terlacak. Yanti tersenyum maklum dan mengantar mereka menuju ke deretan telpon umum yang lengang.
Dina dan Yance ke sebuah stand telpon yang ada di ujung barat.
Setelah Yanti pergi, Dina langsung membuka buku telpon dan membolak-baliknya mencari nama Kwan Chee Wai, tapi tak dijumpainya.
‘Kamu mau menelpon siapa?’ tanya Yance.
‘Kwan Chee Wai,’ jawab Dina. Yance mengeleng-gelengkan kepalanya.
‘Berikan buku itu padaku,’ pinta Yance. Dina mengulurkannya. Yance membalik beberapa halaman dan langsung menemukan nomor telpon toko sepatu Lion.
‘Nih,’ kata Yance sambil menunjukkan sebuah nomor. Dina tersenyum menyadari ketololannya. Kemudian dia memutar nomor tersebut. Terdengar deringan dua kali sebelum telpon di seberang diangkat.
‘Hallo, toko sepatu Lion di sini,’ terdengar suara wanita. Dari logatnya yang medok, Dina tahu kalau dia orang Jawa.
‘Hmm … pelayannya,’ pikir Dina.
‘Saya mau bicara dengan…’ Dina mencari nama Kwan Chee Wai di kertas kumal Dina, tapi tidak ketemu.
‘Kwan Chee Wai,’ bisik Yance.
‘Saya mau bicara dengan Kwan Chee Wai,’ kata Dina tanpa berusaha memakai embel-embel bapak, tuan, engkong atau babah di depan nama Kwan Chee Wai.
‘Ada perlu apa?’ tanya si pelayan kenes. ‘Tapi babah lagi sibuk itu, mbok nanti sore nelponnya,’ suara si pelayan kemayu. Dina diam sejenak.
‘Saya tidak mau tahu apakah dia sibuk atau tidak. Saya butuh Kwan Chee Wai sekarang juga. Ini menyangkut masalah hidup dan mati. Sana lari panggil dia!’ bentak Dina menakut-nakuti. Yance memandang Dina sambil tersenyum lebar.
‘Baik saya panggilkan tunggu sebentar,’ kata pelayan itu gemetar. Dina tertawa. Beberapa saat kemudian terdengar suara seorang laki-laki.
‘Hallo, saya Kwan Chee Wai, bicala dengan sapa ya saya?’ Dina, hampir tertawa mendengar irama suaranya, tetapi dengan keras ditahannya agar tawanya tak keluar.
‘Tak perlu tahu siapa saya. Sekarang saya ingin kamu mendengarkan apa yang akan saya omongkan,’ kata Dina angker. Orangnya yang ada di seberang tak mengeluarkan suara apa-apa. Dina membayangkan orang itu pasti gemetar ketakutan karena bentakannya.
‘Kamu punya anak yang namanya Kim Fui? “
‘Iya, benal,’ jawab Kwan Chee Wai gagap.
‘Hmm…’ dengus Dina. kamu pasti tak pernah mengajar adat kepada anakmu yang satu ini. Kamu merasa kaya ya? kamu bangga anakmu dapat berbuat sesuka hati dan menghina orang seenak perutnya sendiri,’ kata Dina dalam nada tinggi.
‘Nona, saya olang kagak ngalti apa nyang nona bicalaken.’
‘Kamu dengar tidak peristiwa di Ujung Pandang tentang pelemparan batu pada rumah-rumah milik orang Tionghoa? Na, kejadian semacam itu bisa terjadi di Yogya lantaran anakmu,’ ancam Dina.
‘Tapi nona, saya olang punya anak tidak ada nyang kulangajal. Itu cuma pietnah. Jangan didengalken,’ Dina tertawa sinis mendengar penuturan Kwan Chee Wai.
‘Bukan fitnah. Anakmu yang namanya Kim Fui, kemarin pagi jam tujuh kurang seperempat telah menghina seorang gadis anggota kelompok kami, seorang Indonesia asli yang masih berdarah ningrat dan ayahnya pemimpin partai besar dengan meludahinya di bawah Kretek Kewek.’ Dina sengaja meninggikan diri agar kedengarannya lebih berwibawa.
Kwan Chee Wai terdiam sesaat. Akhirnya dia bicara.
‘Maafkan dia olang, nona. Nanti dia olang pasti akan saya beli pelajalan. Saya beljanji untuk menghajal itu anak,’ katanya makin ketakutan.
‘Itu thok tidak cukup,’ potong Dina tajam.
‘Telus bagaimana saya olang halus pelbuat? “
‘Saya atas nama kelompok anak muda Yogya minta pernyataan tertulis di surat kabar. Saya tidak minta yang aneh-aneh, cukup di surat kabar lokal saja. Paling lama lusa harus sudah terbit. Lengkap dengan nama Kim Fui dan toko sepatu Lion,’
kata dina. Yance membelalakkan matanya mendengar apa yang diucapkan Dina.
‘Tapi nona, kami olang punya nama akan telcemal gala-gala ini pelkala.’
‘Terserah kamu. kamu tulis di surat kabar atau kamu sendiri harus menanggung resikonya. Dan sekali lagi saya peringatkan bukan hanya keluargamu saja yang mungkin menderita akibatnya.’
‘Oe nona, saya mekelum,’ kata Kwan Chee Wai.’Dan kalau saya boleh tahu nona punya nama sapa?’
‘Saya wakil dari anak-anak muda kota Yogya,’ jawab Dina rendah sambil meletakkan gagang telpon. Dia tersenyum puas dan mengajak Yance berlalu.
‘Apa yang kamu perbuat benar-benar keterlaluan,’ komentar Yance sambil berjalan. ‘Bagaimana jika dia lapor ke polisi? “
‘Biarkan dia lapor ke polisi. Polisi tak kan mampu melacak kita. Lagi pula aku tidak melakukan kejahatan, apa yang kulakukan tidak melanggar hukum. Dia bersalah, maka dia harus minta maaf. Hal yang sepele.’
‘Tapi kamu mengancam dia.’
‘Aku tidak mengancam. Hanya kukatakan apa yang terjadi di Ujung Pandang bisa terjadi di Yogya. Kan benar? “
‘Tak tahu deh, Din. Cuma kubayangkan bagaimana jika yang menerima telpon tadi keluargaku. Apa tidak akan geger? kamu sadis banget sih,’ kata Yance. Kemudian yance melihat jam yang melilit di pergelangan tangannya.
‘Ya… telat, Din!’ teriak Yance. Kemudian mereka bergegas menuju sekolah mereka. Sesampai di depan pintu kelas mereka berpandang-pandangan ragu.
‘Masuk enggak?’ tanya Yance.
‘Masuk aja yuk,’ Dina memutuskan. Dengan berjingkat mereka masuk kelas.
‘Dari mana anak-anak manis?’ tegur bu Dariah guru kimia mereka. Dina dan yance tersenyum lucu, sementara teman-teman mereka bersiul-siul.
‘Maaf bu, enggak dengar bel tadi,’ alasan Dina.
‘Kumaafkan asal kamu bisa mengerjakan soal itu,’ kata bu Dariah sambil menunjuk soal yang ada di papan tulis. Dina membelalak. Teman-temannya cengar-cengir dan menggodanya. Dina kemudian melihat Ah Yong mengisyaratkan agar dia memakai bukunya.
‘Huh, China itu pasang aksi,’ kata hatinya. Kemudian dia menuju papan tulis mencoba mengerjakan soal. Lama sekali tak berhasil. Dia menoleh ke belakang. Yance telah duduk rapi di kursinya, dia memberi tanda agar Dina menerima buku Ah Yong.
‘Bagaimana Dina?’ tanya bu Dariah.
‘Sukar, Bu. Nyerah aja deh,’ kata Dina seperti anak kecil. Bu Dariah tertawa ringan.
‘Ah guru ini selalu manis,’ pikir Dina ketika bu Dariah menyuruh duduk.
‘Yong, kamu bisa?’ tanya bu Dariah pada Ah Yong. Ah Yong terus bangkit menuju papan tulis dan mengerjakan soal itu dengan cepat.
‘Kenapa kamu tak mau menggunakan buku Yong?’ tanya Yance. Dina menatap Yance lama sebelum menjawab.
‘Ingat dia orang China dan aku sudah berjanji tak akan berhubungan lagi dengan segala macam China,’ bisik Dina.
‘Din, jangan keterlaluan. Yong tak punya kesalahan apapun terhadapmu.’ Yance menasehati, tetapi telinga dina seakan tak mempunyai lubang.
Keesokan harinya, permintaan maaf dari toko sepatu Lion telah nampang di Koran. Dina mengambil gunting dan mengguntingnya lalu di tempelkan di buku kenangannya. Hatinya mekar karena telah berhasil membalas dendam. Tetapi kalau ada anggapan bahwa pernyataan itu sebagai akhir dari sikap sinis Dina terhadap orang-orang Tionghoa maka anggapan itu salah besar.
Sikap Dina semakin tak masuk akal. Apa-apa yang berbau China dianggap haram. Dia tak mau menggunakan handuknya lagi karena handuknya itu made in China. Dia lebih baik tak pergi ke restaurant langgannannya karena pemiliknya orang Tionghoa. Dan dia tidak lagi suka berjalan-jalan sepanjang jalan solo dan Malioboro karena dia segan untuk bertemu dengan orang Tionghoa. Bahkan kepada ah Yong yang duduk di belakangnya di kelas dia tak suka menegur.
‘Din, kamu tak percaya bahwa ada orang Tionghoa berhati baik?’ tanya Yance suatu hari.
‘Sudah ratusan kali kubilang Yan, semua China sama saja. Cuma mau cari untung. Mereka menyeberang dari tanah China karena ada huru-hara di negerinya sehingga mereka merasa tidak aman lagi, tetapi rasa cinta mereka tetap ada di tanah leluhurnya. Sedang Indonesia dianggap sebagai tempat untuk mencari nafkah. Bukan sebagai tanah tumpah darah.’
‘Tapi kebanyakan mereka dilahirkan di sini.’
‘Benar. Tapi jangan lupa, orang-orang tua mereka telah mengajarkan filsafat yang kuat di hati mereka untuk tetap mencintai negeri asalnya,’ bela Dina.
‘Pernahkah kamu renungkan, orang-orang seperti Cuncun, Rudi Hartono, Liem Swie King membawa nama Negara kita dari pada kamu sendiri yang mengaku orang Indonesia asli. Benar kan?’ tanya Yance. ‘Bahkan Cuncun walaupun sampai sakit begitu masih
mau berkorban untuk Negara. Apakah mereka kamu anggap Cuma mau cari untung saja?’ lanjut Yance.
‘Ah, mereka lain. Mereka berkecimpung dalam bidang olahraga jadi dengan sendirinya memiliki jiwa yang sportif. Bukan seperti lainnya yang ngurusin dagang melulu,’ bela dina ngawur.
‘Oke, berarti ada China yang baik,’ Yance menegaskan.
‘Aku tak mengatakan demikian,’ bantah Dina.
‘Tapi kamu merasa bangga terhadap Rudi Hartono cs kan?’
‘Jangan samakan mereka dengan yang lainnya !’
‘Berarti kamu tidak fair.’
‘Yan, aku tahu kamu tak akan bisa menempatkan dirimu pada posisiku. Aku pernah diludahi China. Itu menyakitkan. Panas matahari ditanggung semua orang, tetapi panasnya hati … ya aku sendiri yang menanggungnya. Walaupun kamu sahabatku yang paling dekat kamu tak kan bisa ikut merasakan panasnya hatiku,’ kilah Dina befalsafah
‘Bukankah dia telah minta maaf? Sedang Tuhan saja maha pemaaf kenapa kamu tidak bisa memaafkannya. Bagaimana jika orang yang meludahimu itu dulu orang Jawa, sukumu sendiri. Apakah kamu akan membenci semua orang Jawa seperti saat ini kamu membenci orang China?’ kata Yance bersemangat. Dina diam saja. Kalau sudah demikian biasanya mereka mengganti topik pembicaraan, karena menurut pengalaman, mereka tak pernah menemukan titik temu pendapat mengenai hal yang satu ini.
Siang itu panasnya bukan main. Terik matahari benar-benar menyengat badan. Selama perjalanan pulang dari sekolah, Dina berkali-kali mengosok lengannya dengan telapak tangan karena rasanya seperti terbakar. Dia merasa begitu lega ketika memasukkan sepeda motornya ke halaman rumahnya yang penuh dengan pepohonan rindang. Dina langsung masuk kamar tidurnya setelah memasukkan sepeda motornya di garasi karena kedua orang tuanya belum pulang. Jadi dia terhindar dari kewajiban untuk makan siang terlebih dahulu. Kemudian dia membaringkan dirinya di kasurnya yang empuk tanpa mengganti pakaian seragamnya. Matanya menatap langit-langit kamarnya kemudian berpindah ke seantero kamar.
Tiba-tiba matanya melihat laptopnya di atas meja belajar. Langsung dia beranjak dan menyambar laptop itu kemudian kembali ke kasurnya untuk mencek facebook dan e-mail. Ada satu e-mail yang menarik perhatiannya
‘Hmm … sudah lama Sasa tak kirim e-mail,’ gumamnya. Sasa adalah kakaknya yang kini meneruskan belajarnya di Amerika.
Seperti biasa kalau Sasa mengirim e-mail akan panjang lebar. Tetapi karena yang ditulis selalu menarik maka tidak pernah membosankan. Pada paragraf pertama Sasa menulis tentang keadaannya dan sekolahnya. Paragraf kedua tentang mode yang sedang melanda muda-mudi Amerika. Dilanjutkan tentang pekerjaan sambilannya di Mc Donald Hamburger Corner dan di bagian akhir dia menulis…
‘Eh, Din, Sasa barusan nonton film yang diputar oleh televisi kalau enggak salah NBC yang mutar. Seluruh penghuni asrama sini nonton. Pertunjukannya memakan waktu enam jam (ini sudah termasuk iklan yang setiap lima belas menit sekali nongol), jadi terpaksa harus diputar selama empat malam berturut-turut. Judulnya hOLOCAUST (ingat-ingat deh, siapa tahu diputar di Indonesia).
Nah ini cerita tentang keluarga Weiss yang Yahudi dalam masa sadis-sadisnya hitler. Aduh berkali-kali deh Sasa terpaksa menutup mata … Ngeri. Bayangin deh, mama Weiss dan wanita-wanita lain disuruh masuk ke kamar mandi, waktu itu mereka sudah di penjara, katanya disuruh mandi tapi begitu pintu kamar mandi ditutup dan mereka sudah ditelanjangi eh tahunya yang keluar dari shower itu uap beracun. Mereka menggeliat-geliat sebelum mati. Masih banyak deh Din, yang sadis-sadis lainnya, misalnya disuruh baris menghadap ke tembok, enggak laki-laki, enggak perempuan dan deeerrr … Akhirnya tinggal seorang keluarga Weiss yang hidup. Anak laki-lakinya dan dia terpaksa mengungsi. Gila nggak tuh si Hitler? kamu tahu enggak teman-temanku yang punya mata berwarna biru sampai menyesal mempunyai mata biru akibat nonton film itu. Habis semua mata biru di situ sadis sih. Apalagi yang orang Jerman … wah tak henti-henti menyesali kekejaman bangsanya waktu itu.
Din … Yance bilang kamu kini musuhan ya sama orang-orang Tionghoa? Jangan dong, Din. Hitler itu juga dulunya cuma berawal dari rasa tidak senangnya terhadap orang-orang Yahudi tanpa alasan yang kuat hingga dia sesadis itu. Sasa pikir kalau adik Sasa yang Cuma gadis manis biasa saja berani ngancam orang Tionghoa apalagi Hitler yang punya kekuasaan.
Orang-orang Tionghoa itu seperti halnya orang Yahudi lho Din (ah, ini perbandingan saja) mereka akan membela Negara di mana mereka mendapatkan ketentramannya. Dalam hal ini Indonesia tentu saja. Kalau kamu sudah sejak dini memusuhi mereka bagaimana nanti jika kamu sudah menjadi pemimpin bangsa (bukankah itu cita-citamu). Ayo, Din hilangkan sikap prejudismu. Setiap bangsa itu sama saja, punya kelebihan dan punya kekurangan. Memang ada satu orang Tionghoa yang cuma mau cari untung, tapi harap kamu ingat orang Indonesia yang mau menangnya sendiri tak kalah banyaknya. Biasakanlah dirimu menerima seseorang itu apa adanya. Jangan kamu lihat bangsa dan derajatnya.
Oke, Din aku tahu kamu adikku yang berhati manis. kamu pasti akan bersikap seperti dulu lagi. Udah ya Sasa bobo dulu.’
‘Uih, Yance, pakai lapor segala,’ gumam Dina, tapi dia segera tertidur karena lelah. Dia baru terbangun ketika merasa tubuhnya digoyang-goyangkan. Kemudian samara-samar dia mendengar suara panggilan dari mamanya.
‘Udah disamperin Yance tuh,’ kata mama Dina. Dina bangun dan duduk dengan lesu.
‘Kalau tidur ganti baju dulu dong,’ omel mamanya.
‘Yance? Mau apa dia ke sini?’ tanya Dina tak mengacuhkan kata-kata mamanya.
‘Katanya ada pertandingan antar SMA di …’
‘O iya,’ jerit dina sambil meloncat turun dari tempat tidurnya dan langsung berlari ke luar, tetapi segera kembali ke kamarnya lagi.
‘Tolong deh, Mam, temenin Yance sebentar, Dina mandi dulu,’ katanya. Mamanya mengeleng-gelengkan kepalanya dan tersenyum.
Ketika dina keluar dengan pakaian olahraganya, Yance dan mamanya sedang asyik bercakap-cakap. Ada segelas susu dan sebutir telor rebus di atas meja di hadapan mereka. Dina pura-pura tak melihat, karena dia tahu semua itu pasti untuknya .
‘Aku gonceng saja ya, Yan, aku masih agak ngantuk?’ kata Dina. Yance mengangguk sambil berdiri.
‘Susu dan telormu , Din,’ mama dina mengingatkan.
‘Ya, mama. Dina masih kenyang,’ protes Dina.
‘Bibi bilang kamu langsung tidur tadi, jadi belum makan siang. kamu makan telormu atau kamu ingin makan siang?’ akhirnya dina menurut. Dia memakan telornya dengan cepat dan meneguk susunya. Kemudian melambai kepada ibunya dan keluar.
‘Yan, kamu pakai kirim e-mail ke Sasa tentang diriku ya?’ tanya Dina ketika keduanya telah berada di jalan.
‘Enggak boleh?’ tanya Yance.
‘Kirim e-mail sih boleh aja. Tapi nggak usah tentang yang satu itu,’ kata dina.
‘Habis kamu makin enggak rasional sih. Kamu sok idealis, tapi konyol,’ kata Yance. Dina tertawa.
Ketika mereka sampai di lapangan IKIP Karangmalang, mereka langsung ke jadwal pertandingan.
‘Hei, asyik lawan Stelladuce,’ bisik Dina di telinga Yance. Yance segera mengerti maksud Dina. Pemain-pemain basket Stelladuce kebanyakan anak-anak keturunan Tionghoa. Yance menggeleng-gelengkan kepalanya.
‘Hei, Yakis!’ tiba-tiba terdengar sebuah suara. Yance dan Dina menoleh seketika. Tampak seorang pemuda yang dulu berada di samping Dina ketika dina berhenti di belakang mobil Kim Fui. Kalau dulu dia berpakaian urakan, kini dia berpakaian santai tapi rapi. Yance mengerutkan dahi, merasa tidak senang temannya dipanggil ‘Yakis’. Tetapi Dina justru tersenyum. Yance terus ngeloyor pergi karena sebagai kapten regu basket sekolahnya dia harus mengumpulkan regunya lebih dahulu.
‘Kubaca tentang kamu di surat kabar,’ kata si pemuda.
‘Surat kabar?’ tanya Dina bingung.
‘Pernyataan maaf untukmu,’ kata si pemuda. Dina tertawa. Dia kembali teringat peristiwa itu lagi. ’Senang ya bisa bikin sensasi?’ lanjut si pemuda.
‘Ah, biasa-biasa saja,’ jawab Dina santai. Si pemuda cuma tersenyum mendengar jawaban Dina.
‘Kamu mau bertanding?’ tanyanya.
‘He eh.’
‘Lawan mana? “
‘Stelladuce.’
‘Wah sorry enggak bisa nyeporterin kamu, sudah keburu dibon Selladuce.’
Ah enggak apa-apa, paling juga menang,’ jawab Dina. ’kamu sekolah di mana sih? Bukan Stella Duce kan?’ tanya dina
‘De Britto,’ jawab si pemuda sambil tertawa.
‘Oh, pantas,’ kata dina. Pantas di sini bermaksud banyak … Pantas kalau dia dulu berlagak sok jagoan. Pantas kalau sekarang dia mau nyeporterin stella duce, karena baik Stelladuce maupun De Britto dua-duanya sekolah ‘gersang’ Stella duce cewek melulu dan De Britto cowok melulu, jadi barter dalam hal seporter-seporteran.
Kemudian terdengar Yance memanggil Dina menyuruhnya berkumpul. Begitu Dina sampai di lapangan basket, pertandingan segera dimulai. Walaupun seporter-seporter dari Sella duce dan De Britto cukup banyak dan ramai tetapi toh tetap kalah dibanding dengan Fajar dan kawan-kawannya yang nyeporterin regu Yance. Teriakan-teriakan dari seporter Stella duce tertelan oleh teriakan dari Fajar Cs. Di samping itu, Dina walaupun di tengah permainan masih sempat berteriak-teriak nyeporterin regunya.
‘Ayo, moy-moy lemparkan bolamu pada dina, di tokomu banyak bolanya,’ teriak Dina sambil mendek pemain stella duce yang keturunan Tionghoa. Semua yang berada di pinggir lapangan tertawa mendengar teriakan Dina, kecuali yang merasa diri masih keturunan China. Akibatnya banyak pengikut Stella duce yang berasal dari De Britto yang merasa bukan keturunan Tionghoa menyeberang menjadi pengikut sekolah Dina dan ikut-ikutan mengajak anak-anak Stelladuce.
‘Ayo, Sanchai aku cinta padamu,’ teriak Fajar meramaikan suasana.
‘Bukan aku cinta padamu, tapi wo ai ni,’ teriak Dina sambil melempar bola ke keranjang. Nadanya dibuat persis orang-orang China asli. Tiba-tiba dia teringat apa yang ditulis Sasa di suratnya.
‘Kalau adik Sasa yang merupakan gadis manis biasa saja bisa mengancam orang Tionghoa apalagi Hitler yang punya kekuasaan. ‘Entah mengapa Dina tak mau dirinya disamakan dengan Hitler. Kemudian dia tak banyak komentar-komentar yang menyakitkan hati diserahkan ke tangan Fajar cs, yang dapat melakukannya dengan baik, terbukti sebentar-sebentar gadis-gadis itu wajahnya memerah menahan marah. Dan konsentrasi mereka buyar yang menyebabkan permainan mereka buruk.
Pertandingan itu usai dengan kemenangan pihak Yance dan kawan-kawannya. Mula-mula dina ogah-ogahan tetapi akhirnya mau juga dia menyalami mereka.
‘Sorry ya, kalau kata-kataku tadi kasar,’ kata Dina. Dia tak tahu mengapa dia merasa bahwa dia harus meminta maaf. Yang disalami tersenyum mencoba melupakan kata-kata Dina yang menyakitkan hati selama pertandingan tadi berlangsung.
‘Din, dapat salam dari Huan,’ kata Ah Yong sambil mengucapkan selamat kepada Dina.
‘Siapa?’ tanya Dina bingung
‘Huan. Yang tadi ngomong-ngomong sama kamu sebelum pertandingan.’
‘O, dia namanya Huan? Orang mana sih?’ tanya dina pingin tahu.
‘Orang Yogya. Itu lho anaknya yang punya sepatu Lion.’
‘Apa?’ tanya Dina kaget. Matanya membulat dan lehernya seakan tercekik.
‘Dia memang keturunan Tionghoa kok. Enggak nampak ya?’ kata Ah Yong yang tak mengerti kekagetan Dina yang sebenarnya.
‘Toko sepatu Lion? Adik Kim Fui?’ tanya Dina meyakinkan diri bahwa apa yang didengar telinganya betul adanya.
‘Lho kamu kok tahu? Kenal Kim Fui ya?’ tanya Ah Yong. Dina menggeleng-gelengkan kepalanya mencoba mengusir kekacauan yang tiba-tiba muncul di kepalanya.
‘Oke deh salam kembali,’ kata Dina berusaha tenang. Setelah Ah Yong berlalu Dina berdiri termangu.
‘Jadi dia adik Kim Fui. Berarti dia tahu, akulah yang telah mengancam ayahnya dan memaksa mereka menulis pernyataan maaf di Koran. Tetapi mengapa dia tak memberi tahu ayahnya kalau yang mengancamnya itu tak lain hanyalah seorang gadis yang tak punya kekuatan apa-apa atau tak melaporkannya kepada polisi? Tetapi mengapa di malah menegurku seakan tak ada kejadian apa-apa?‘ pikir Dina bingung.
‘Pulang nggak, Din?’ tegur Yance yang tiba-tiba saja sudah ada disampingnya.
‘Emangnya mau nginap di sini?’ jawab dina dan berjalan bersama Yance.
‘Selama perjalanan pulang pikiran Dina kacau. Dia tak mendengar apa yang diocehkan yance selama perjalanan.
‘Ruwet … ruwet. Mengapa jadi begini? Jadi waktu aku memaki-maki Kim Fui di Kretek Kewek itu, dia sudah tahu kalau yang kumaki adalah kakaknya. Ih, ruwet,’ pikir Dina, setengah menyesali diri.
Sesampai di depan rumah Yance bertanya, ’ikut enggak besok pagi? “
‘Ke mana?’ tanya Dina.
‘Tadi sudah kukatakan padamu dan kamu menjawab ya.’
‘Aku tidak tahu,’ kata Dina. Yance mengerutkan bibirnya jengkel.
‘Jadi kamu tak menggubris omonganku selama perjalanan tadi, di mana sih pikiranmu, Din? Pada Huan, ya? “
‘ kamu tahu siapa dia?’ tanya Dina hati-hati.
‘Tentu saja aku tahu. Adik Kim Fui. Aku heran apa yang akan dilakukannya kalau dia tahu kamu yang telah menganc …’
‘Dia tahu, Yan,’ potong Dina. Yance membelalak tak percaya.
‘Tahu deh, Din, kamu berdua sinting semua. Dia tenang-tenang saja berhadapan dengan musuh keluarganya sementara kamu sendiri juga tenang-tenang dipanggil yakis,’ kata Yance.
‘Karena dia tak tahu arti ’yakis’ yang sebenarnya,’ bantah Dina, tapi tak diucapkan. Dia hanya tertawa ringan.
‘Ada apa besok pagi?’ akhirnya dina bertanya.
‘Ayah dan ibuku serta kakakku datang dan…’
‘Dari Ternate?’ tanya Dina antusias. Dina mengangguk.
‘Mereka sudah ada di Jakarta sejak kemarin dan besok akan datang ke sini jam sepuluh. Nah, kamu mau ikut jemput enggak? “
‘Tentu dong. Ole-olenya itu yang kubutuhkan,’ jawab Dina sambil tertawa sambil membayangkan kue bagia yang penuh dengan kenari, Yance juga tertawa.
‘Kalau begitu kamu harus bangun pagi. Jam setengah sembilan ku jemput kamu?’
‘Siap, kapten,’ kata Dina dan Yance segera menghidupkan mesinnya. Setelah pesan ini itu barulah Yance pergi, meninggalkan
asap yang mengepul dari knalpotnya.
Pagi itu cuaca agak mendung. Dina dan yance telah berada di pelabuhan udara Adi Sucipto. Orang tua serta kakak Yance baru akan tiba setengah jam lagi. Selama menunggu mereka berdua duduk di bawah pohon akasia di luar airport sambil menikmati teh botol
‘Yan, biasanya kalau cuaca begini penerbangan jadi batal lho,’ kata Dina. Yance mencibir.
‘Enggak percaya? Soalnya lapangan ini kan dikelilingi bukit, na, kalau mendung bukit ini enggak begitu tampak, jadi lebih baik penerbangan diundur dari pada ada malapetaka.’
‘Din, aku sudah tanya dan mereka mengatakan sudah take off dari Jakarta.’
‘Wah … berdoa saja deh Yan, moga-moga nggak ada apa-apa,’ kata dina tenang. Yance membelalakkan matanya.
‘Yakis kamu!’ teriaknya. Dina tertawa terpingkal-pingkal.
‘Baru dibilangin begitu saja sudah kalap,’ olok Dina.
‘Orang tua cuma dua kok, masa dibegitukan, ya marah dong,’ kata Yance. Dina masih tertawa ketika terdengar pengumuman bahwa pesawat dari Jakarta baru saja mendarat. Bergegas mereka berlari masuk.
Yance menanti tak sabar. Dia menggerak-gerakkan kakinya siap untuk berlari. Dina yang baru pertama kali ini melihat ketidak-tenangan Yance tersenyum. Satu demi satu para penumpang muncul. Yance memperhatikan mereka satu persatu sementara Dina membayangkan seperti apa wajah orang tua dan kakak Yance.
‘Itu dia,’ kata Yance sambil menunjuk tiga orang yang berjalan ke arah pintu keluar.
‘Yang mana?’ tanya dina karena yang ditunjuk Yance adalah tiga orang Tionghoa.
‘Itu ! Yang dengan gadis berbaju merah,’ kata Yance.
‘Ah, jangan main-main …’ Tapi Yance sudah tak mendengarnya dia sudah berlari mendekati mereka. Menyadari hal itu, jantung Dina seakan berhenti berdetak. Dia memandang mereka berempat bagai memandang mayat yang baru bangkit dari liang kubur. Matanya terbelalak dan mulutnya terbuka lebar.
‘Yance keturunan Tionghoa?’ desisnya lunglai. Dia menginginkan dunia kiamat saat itu juga hingga dia tidak harus berhadapan dengan Yance lagi. Dia tak punya muka untuk menemui Yance, terlalu malu. ’Penghinaan yang selama ini kulancarkan ternyata hanya untuk menyakiti hatinya. Tuhan, berilah aku ampunan,’ pikir Dina sedih. Tapi tak ada jalan lain untuk tidak menemui Yance. Karena untuk melarikan diri jelas tidak mungkin. Dan Yance serta keluarganya sudah mendekati Dina.
‘Dina, Yance selalu bercerita kalau Dina serta keluarga Dina baik sama Yance,’ kata ibu Yance sambil menjabat tangan Dina. Dina hanya bisa tersenyum. Wajahnya sebentar merah, sebentar memucat. Dia ingin mencari kekuatan pada Yance, tapi Yance begitu asyik bercakap dengan kakaknya.
‘Kenapa Yance tak pernah bercerita kalau dia itu keturunan Tionghoa?’ pikir Dina menyesali keadaan. Keluarga Yance begitu ramah, hal mana justru membuat hati Dina semakin pedih. Dia merasa sangat berdosa terhadap Yance.
Ketika orang tua Yance sedang mengurus barang-barangnya, Yance mendekati Dina dan menepuk bahunya.
‘Setelah tahu kalau aku orang China apakah kamu tidak mau bersahabat lagi denganku?’ tanya Yance sambil menahan senyum,’sedang aku yang kamu hina setiap menit saja masih mau berteman denganmu,’ lanjutnya sambil tertawa lirih. Dina memandang Yance dengan sinar mata berisi sejuta penyesalan.
‘Maafkan Dina, Yan, aku tahu aku telah salah selama ini.’
‘Syukur deh kalau kamu sadar.’
‘Jadi kamu memaafkanku? Enggak sakit hati?’ tanya dina mulai agak tenang.
‘Wah maaf thok enggak cukup,’ kata Yance.
‘Lalu?’
‘Aku minta pernyataan tertulis. Enggak muluk-muluk deh, Din, cukup ditulis di surat kabar Indonesia, enggak usah di surat kabar Internasional. Paling lambat lusa harus sudah terbit,’ kata Yance menirukan kata-kata dina beberapa waktu yang lalu ketika mengancam Kwan Chee Wai melalui telpon. Dina dan Yance tertawa. Mereka masih tetap tertawa waktu keluarga Yance siap untuk meninggalkan airport. Mendung yang tadi melingkupi kota Yogya telah hilang dan matahari bersinar dengan ramah.
Note: Isi tidak berubah walau di sana-sini sudah disesuaikan agar tidak terlalu kuno …
Posted in Short Stories
Tags: Cerpen, Fiksi, Gadis, Laily Lanisy, Nafas Muda Kota Yogya
Be My Valentine
Posted by Laily Lanisy
Steve berjalan di depanku sambil menarik sled, kereta salju berwana merah menyala. Dari mulutnya terdengar siulan Poker Face-nya Lady Gaga. Sesekali dia menoleh ke belakang, melihat kalau-kalau aku sudah tertinggal jauh. Bila jarakku dengannya lumayan jauh dia akan menghentikan langkahnya dan memandangku sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dengan lucu. Bila sudah demikian aku merasa tertantang dan kupercepat langkahku.
‘Capai, Princess?’ tanya Steve ketika melihat langkahku mulai tidak karuan. Berjalan di salju yang begini tebalnya memang sulit. Sudah dingin, berat lagi, sehingga kaki malas untuk bergerak.
‘Duduklah di atas sled ini, nanti kutarik,’ usul Steve. Kakak AFS-ku yang satu ini memang selalu manis dan penuh perhatian. Aku menggeleng. Aku belum terlalu gila untuk membiarkan dia setengah mati menarikku seentara aku enak-enak duduk.’
‘Nggak mau ah. Nggak lucu,’ tolakku. Steve mengangkat bahu sambil meneruskan langkahnya lagi. Poker Face-nya kembali terdengar. Tiba-tiba kami melihat sebuah truk berhenti di jalan jauh di depan kami.
‘Nasib kita sedang mujur, Princess,’ seru Steve, ‘truk itu kelihatannya menunggu kita,’ lanjutnya sambil menarik tanganku dengan tangan kirinya agar aku bisa berjalan lebih cepat.
“Hai !!!’ teriak Steve setelah kami agak dekat dengan truk tersebut, ‘Boleh kami numpang?’ tanyanya, Sebuah kepala tersembul keluar dari jendela. Mati aku!!!
Kepala yang tersembul keluar dari jendela truk itu ternyata milik Timothy Clements, manusia paling kubenci di negerinya Obama ini. Jauh-jauh dari Indonesia aku datang ke negeri ini dengan berbekal cinta selautan India, tanpa seujung kuku kebencian. Kecuali untuk manusia bernama Timothy Clements ini. Aku tidak bisa membendung rasa ketikdaksukaanku terhadapnya. Aku tahu ini tidak sesuai dengan motto “AFS is Love…AFS is brotherhood”. Tapi mau dibilang apa, perasaan itu muncul dengan sendirinya. Semakin hari semakin kuat, tanpa perlu dipupuk dan disemai.
♥
Aku tidak bisa melupakan pertemuan pertamaku dengannya. Hari itu hari pertamaku masuk sekolah. Semuanya serba baru dan asing, sehingga sedikt membuatku grogi. Pada waktu aku berdiri di depan pintu masuk tiba-tiba saja bel berdering dengan nyaringnya. Semua murid yang masih berada di halaman sekolah berlarian masuk dan melewatiku. Tiba-tiba seseorang menabrakku dari belakang. Semua buku dan ballpoint yang berada di tanganku jatuh dan berserak di bawahku. Belum lagi hilang rasa kagetku, pemuda yang menabrakku tadi berteriak.
‘Hei, tolol, jangan berdiri di depan pintu!’ Kupandang dia sekejab dan dalam hati aku berkata, aku tidak akan pernah melupakannya. Aku benar-benar sakit hati. Pelan-pelan aku menunduk dan memunguti buku-bukuku.
‘Jangan dengar omongannya,’ tiba-tiba seorang gadis telah berjongkok di depanku dan membantuku mengumpulkan buku-bukuku. Gadis tersebut kemudian kukenal sebagai Andrea Simons.
‘Itu tadi Tim. Timothy Clement,’ Andrea menerangkan, ‘murid paling urakan di sekolah ini. Dia pikir semua anak menyukainya karena dia cerdas dan bintang lapangan. Itulah sebabnya omongannya sering ngawur dan seenaknya. Engkau tidak perlu menggubrisnya,’ saran Andrea. Saran itu kemudian kuturuti dengan baik. Aku tidak pernah menggubrisnya. Sama sekali tidak pernah. Tersenyum padanya pun aku belum pernah, apalagi meluangkan waktu untuk bertegur sapa. Padahal banyak kelas-kelasku yang sama dengan kelasnya. Bahkan, pada mata perlajaran American Government, Tim duduk tepat di belakangku.
Dan kini kami akan numpang truknya? Aduh, harus kubuang kemana gengsi ini?
‘Steve, kita jalan kaki saja,’ bisikku pada Steve. Steve membelalakkan matanya tidak percaya. Tim yang mendengar bisikanku tersenyum lebar sambil membuka pintu truk-nya.
‘Cepat naik, Princess. Kamu bisa mati kedinginan di situ. Lihat, wajahmu sudah kebiru-biruan,’ ucap Tim. Aku benar-benar dongkol mendengar dia ikut-ikutan memanggilku Princess, panggilan sayang keluarga Amerikaku yang tidak bisa melafalkan namaku dengan benar.
‘Ayo, Princess!’ ajak Tim lagi. Tiba-tiba angin berhembus dari utara. Brrrr…. dinginnya. Terpaksa kuturuti ajakan Tim, meloncat naik ke dalam truknya dan duduk di sampingnya.
Selama perjalanan, aku diam bak patung Rara Jonggrang. Dingin dan angkuh. Semua perkataan Tim, Steve yang menimpalinya. Tak sekalipun aku menyumbang suara. Steve pula yang bercerita kalau kami baru saja pulang dari Sled Riding di bukit di belakang sekolah dan pulangnya ingin mengukur kekuatan dengan berjalan kaki…. dan ternyata tidak kuat.
‘Kamu bisa bermain sled, Princess?’ tanya Tim. Kudiamkan.
‘Oh, dia mahir,’ Steve yang menjawab. Aku tahu Steve merasa tidak enak mendengar pertanyaan Tim hilang ditelan keheningan.
‘Kalian ikut main ski di Crystal Mountain tanggal 12 yang akan datang?’ tanya Tim beberapa saat kemudian.
‘Ya,’ jawab Steve mantap. ‘Kamu ikut?’ sambung Steve dengan pertanyaan. Tim mengangguk sambil tersenyum. Aku berdoa agar cepat sampai di rumah sehingga tidak harus mengunci mulut macam ini.
Begitu sampai di depan halaman rumah, aku segera turun dan berlari meninggalkan Tim. Aku yakin Steve akan mengucapkan terima kasih untuk kami berdua, jadi aku tidak perlu mengucapkannya.
‘See you, Princess!’ teriakan Tim terdengar sebelum aku menghilang di balik pintu garasi. Sepatu boot kulepas di depan pintu dapur. Mom bisa histeris kalau aku masuk dapur dengan sepatu itu. Lantai dapur kami selalu dalam kondisi mengkilat tanpa noda.
‘Astaga, Princess, ada apa denganmu?’ seru Steve yang telah menyusulku sambil meletakkan sled di sudut garasi. ‘Kamu tidak mendadak menjadi bisu kan?’
‘Steve, kamu tahu jawabnya dengan pasti,’ sahutku sambil masuk ke dapur. Mom dan Robby yang ada di dapur menoleh ke arahku.
‘Hello, sudah pulang?’ tegur mereka serentak.
‘Ya,’ jawabku sambil melepas topi dan kaus tangan. Kugerak-gerakkan badanku untuk menghilangkan dinginnya udara luar.
‘Cepat mandi air hangat. Kalian terlalu lama bermain di luar,’ perintah Mom. Cepat-cepat aku berlari ke lantai atas untuk mandi.
♥
Kembali ke dapur kujumpai Robby tengah menggunting kertas merah muda menjadi guntingan-guntingan berbentuk hati. Begitu melihatku Robby langsung beranjak dari kursinya dan mengambil segelas cokelat susu panas lengkap dengan marshmallow. Gelas itu lalu diulurkannna kepadaku.
‘Untukmu, Princess,’ ucapnya. Aku heran.
‘Kok tumben? Kamu membuatku curiga, Rob. Biasanya kamu tidak semanis ini,’ komentarku.
‘Pasti ada apa-apanya,’ tebak Mom. Rob tersenyum dan dari senyuman itu aku tahu kalau tebakan Mom tepat.
‘Rob, aku mau juga segelas,’ kata Steve yang tiba-tiba muncul di dapur.
‘Buat sendiri,’ sahut Robby acuh. Steve tertawa keras, kemudian berjalan mendekati Robby dan meninju punggungya. Terpaksa dia harus membuat sendiri minuman yang diinginkannya.
‘Kamu bikin apa, Rob?’ tanyaku sambil duduk di dekat Robby dan mengambil salah satu hati kertasnya.
‘Kartu Valentine,’ jawab Robby sambil mengulurkan selembar kertas degan tulisan tangannya
‘Apa ini?’ tanyaku keheranan.
‘Kamu tahu tulisanku jelek dan sulit dibaca, Princess. Sementara tulisan tanganmu sangat indah. Aku ingin mengirim kartu ini untuk gadis yang sangat istimewa. Aku tidak ingin dia tahu kalau tulisanku kacau. Aku minta tolong kamu untuk menuliskan kata-kataku ini,’ Robby menjelaskan. Mom dan Steve tergelak mendengar kata-kata Robby. Robby tetap menjaga sikap kalemnya seakan tidak mendengar gelak tawa ibu dan kakaknya.
‘Jadi ini nih upah membuatkan coklat susu tadi?’ tanyaku.
‘Ya, you can put it that way,’ sahut Robby tanpa sungkan-sungkan. Karena coklat susu sudah terlanjur kuminum, maka tidak ada jalan lain kecuali memenuhi permintaan Robby. Kusalin tulisan tangan Robby yang persis cakar ayam ke atas kertas merah mudanya. Kata-kata cinta Robby untuk gadis istimewanya benar-benar puitis. Lebih puitis dari lagu-lagunya Sheila on 7. Barangkali Robby mendapatkan kata-kata itu dari internet. Rasa-rasanya mustahil, Robby yang umurnya belum genap sebelas tahun bisa menuliskan kata-kata yang begitu cantik. Mau juga aku menerima kata-kata cinta seperti ini dari seorang pemuda. Biarpun pemuda itu mengambil kata-kata orang lain di internet.
‘Princess,’ panggil Mom begitu aku menyelesaikan tulisanku. ‘Kamu sudah menemukan Valentine-mu?’
‘Sudah!’ jawab Steve cepat. Kupelototi dia, tapi dia malah senyam-senyum kayak monyet dilemparin kacang rebus.
‘Siapa?’ tanya Mom dan Robby antusias.
‘Nggak marah kalau kukatakan kepada mereka?’ Steve meminta persetujuanku.
‘Steve, jangan mengada-ada,’ ancamku
‘Aku tidak mengada-ada. Apa yang mengantar kita tadi bukan Valentine-mu? Kalau bukan mengapa duduk di sampingnya saja membuatmu bisu?’ oceh Steve. Aku benar-benar gondok mendengar argumentasi Steve. Teganya dia menuduhku seperti itu. Kuambil spidol-spidol Robby dan kulemparkan ke arahnya. Dalam kesibukannya melindungi wajahnya dari spidol-spidol terbang itu, Steve masih sempat tertawa gelak. Uggh… menyebalkan!!!
♥
Tanggal sebelas Februari pagi, rombongan kami meninggalkan halaman parkir sekolah menuju ke Crystal Mountain, yang letaknya tidak jauh dari kawasan Mount Rainier National Park. Rombongan kami terdiri dari dua puluh delapan anak yang tergabung di dalam ski club dan dua guru pengawas yang kesemuanya mahir bermain ski (kecuali aku tentu saja). Kami akan mengadakan kegiatan ski di sana selama dua hari. Tanggal 13 sore kami akan pulang sehingga kami bisa merayakan Valentine’s Day di rumah. Namun, rencana tinggal rencana.
Dua hari pertama kami bisa melakukan kegiatan ski dengan baik. Udara bear-benar indah, dengan matahari yang bersinar cemerlang. Tetapi di hari ketiga, cuaca berubah drastis. Sejak dini hari salju turun dengan lebatnya, sesekali disela dengan hujan deras. Mulai jam enam pagi terjadilah badai salju yang seakan tidak pernah mau berhenti. Angin menderu-deru, menggoyang-goyangkan pohon besar ke sana ke mari. Kami tidak bisa keluar dan terkurung di penginapan kami. Dari televisi kami mendengar berita bahwa sebagian besar jalan di Negara Bagian Washington ditutup. Apalagi jalan menuju ke puncak-puncak pegunungan seperti ke Crystal Mountain ini. Tidak mungkin bagi kami untuk pulang ke Seattle. Lagi pula bis yang kami tumpangi telah terkubur salju di halaman parker penginapan.
‘Seharusnya salju tidak turun begini lebat di bulan Februari,’ kudengar sebuah komentar di belakangku. Saat itu aku sedang berdiri di depan jendela kaca sambil memperhatikan salju yang berputar-putar dipermainkan angin. Aku menoleh. Tim ada di belakangku ikut menyaksikan apa yang aku saksikan.
‘Kamu sudah menelpon keluargamua kalau kamu tidak bisa pulang hari ini?’ tanya Tim penuh perhatian. Aku bisa saja membiarkan pertanyaannya tidak terjawab. Tapi entah mengapa aku tidak tega untuk melakukannya.
‘Steve telah menelp0n tadi,’ jawabku. Tiba-tiba Tim mengembangkan senyumnya.
‘Kamu tahu, Princess, itu tadi kalimat pertama yang kamu ucapkan kepadaku,’ kata Tim dengan senyuman yang masih berkembang di bibirnya. Aku terdiam. ‘Aku tidak pernah mengerti mengapa kamu tidak pernah mau bicara kepadaku. Semua anak di sekolah mengatakan kalau kamu ramah dan banyak omong. Ratusan kali aku memancingmu untuk berbicara, tapi kamu seakan tidak mau tahu. Ada apa sebenarnya?’
Kupandang dia sejenak. Jadi kamu tidak tahu kalau aku membencimu? Kamu tidak tahu kalau kamu dulu pernah menyinggung perasaanku? Tapi semua itu hanya kubatin, tidak kuucapkan.
‘Tidak ada apa-apa,’ jawabku.
‘Kalau tidak ada apa-apa mengapa kamu tidak pernah mau bicara atau menjawab pertanyaanku?’ kejar Tim tidak puas. Untung saat itu Michelle dan Debby memanggilku untuk bergabung bersama mereka main monopoly, sehingga aku terhindar dari keajiban untuk menjawab pertanyaan Tim.
‘Sebentar, Princess,” ucap Tim menghadangku.
‘Apakah … apakah?’ Tim kelihatan ragu untuk melanjutkan. ‘Apakah kata-kataku di hari pertamamu di sekolah dulu sangat menyakitkan hatimu?’ akhirnya mampu juga dia meneruskan kalimatnya. Jantungku berhenti berdetak. Na……., akhirnya kamu tahu juga.
‘Ya, pasti itu sebabnya,’ gumam Tim. “Princess, maafkan aku. Saat itu aku benar-benar terburu-buru. Guru di homeclassku sangat keras. Telat sedetik pun kami harus minta surat ijin dari administrasi. Aku ingat waktu itu aku bersikap kasar terhadapmu. Maukah kamu memaafkanku, Princess. Please …,” pintanya. Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Memaafkan dia?
♥
Puncak dari badai itu terjadi di malam hari. Di saat kami sudah berada di kamar masing-masing seiap dengan mimpi tentang Valentine besok pagi. Di tengah menderunya angin dan berisiknya pohon yang bertumbangan, tiba-tiba aliran listrik di seluruh penginapan terputus, berarti sebentar lagi kami semua akan kedinginan tanpa pemanas listrik.
‘Tetaplah disini, Princess, aku akn mencari lilin sebentar,’ pesan Andrea yang tidur sekamar denganku.
Sekeluar Andrea aku duduk mematung di atas tempat tidurku sambil mendengarkan angin yang menderu mengerikan seakan sanggup untuk menerbangkan semua yang ada di atas bumi ini. Tiba-tiba kudengar suara benda yang sangat berat jatuh dari atap disusul gemerincing suara kaca pecah. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi karena diselilingku hanyalah kepekatan. Tetapi sejenak kemudian aku mulai merasakan lelehan salju menyentuh kulitku. Astaga, yang jatuh tadi ternyata atap. Aku harus segera keluar dari kamar.
Aku bangkit dari tempat tidurku. Tetapi begitu kakiku menyentuh lantai, secara refleks terangkat lagi. Kakiku terasa nyeri luar biasa. Kusentuh dengan tanganku dan kudapatkan potongan kaca menancap di sana. Pelan-pelan dan sambil menahan rasa sakit, kucabut potongan kaca itu. Untung keadaan kamarku gelap gulita, sehingga aku tidak bisa melihat darah yang mungkin mengalir dari telapak kakiku. Kalau tidak, bisa pingsan aku.
‘Princess! Princess!! tiba-tiba kudengar teriakan-teriakkan memanggil namaku. Juga kulihat sinar-sinar lampu senter yang menyorot kesana kemari. Dan akhirnya singgah di wajahku.
‘Oh, my God!’ kudengar sebuah seruan yang aku yakin berasal dari Tim. Kejadian yang berlangsung sesudahnya sangat cepat. Tim melepas T-shirt yang dikenakannya untuk membungkus kakiku yang ternyata sudah penuh dengan darah. Kemudian dia dan Steve membawaku ke lobby dimana semua temanku berkumpul di sekitar tungku api. Mereka semua lantas mengerumuniku dan memberondongiku dengan pertanyaan apakah aku tidak apa-apa, sementara Mr Toda dan Miss Morris mengganti T-shirt Tim dengan perban.
Sesudah lukaku bersih, Joe, si manager malam hotel, memberiku segelas kecil anggur untuk menenangkanku dan sebuah kamar di lantai dasar dengan pemanas api yang menyala hangat. Entah karena pengaruh anggur, malam itu aku bisa tidur nyenyak sementara kawan-kawanku terpaksa tidur di lantai lobby di sekitar tungku api. Bukan salahku jika aku harus terkena pecahan kaca.
♥
Pagi harinya cuaca kembali seperti semula. Cerah dan tenang. Badai telah berlalu. Yang ada sekarang hanyalah nyanyian burung yang bercanda di bawah sinar matahari.
Ketika keluar dari kamarku dengan kaki yang masih agak pincang, aku disambut dengan ciuman-ciuman dan ucapan ‘happy valentine’ dari mereka-mereka yang semalam tidur di lantai tapi kini toh mereka mempunyai wajah yang cerah. Wajah cinta. Wajah Valentine. Tetapi aku tidak menjumpai satu wajah di sana. Dimana dia?
‘Siapa yang kamu cari?’ tanya Steve.
‘Valentine-ku,’ sahutku.
‘Aku disini …,’ tiba-tiba Tim telah berdiri di depan pintu dengan bungkusan berbentuk hati berwarna merah muda dengan pita berwarna merah menyala di tangannya. Aku tidak tahu bagaimana warna mukaku saat itu. Malu bercampur senang. Tim kemudian berjalan mendekatiku. Diulurkan bungkusan yang dibawanya itu kepadaku.
‘Be my Valentine,’ ucapnya lirih tapi pasti. Memang ucapannya itu tidak sepuitis ucapan Robby kepada gadis istimewanya, tapi bagiku ucapan itu tidak kalah indahnya. Dan ketika Tim memberiku ciuman di pipiku, aku tahu aku telah menemukan Valentine-ku.
Happy Valentine, everybody.
Posted in Short Stories
Tags: Jadilah Valentine-ku, Laily Lanisy, Novelette, Stories, Valentine